MALAM Sabtu awal Rajab ini, hujan turun deras sekali. Lelaki yang berumur nyaris kepala empat itu, baru saja pulang dari aktivitasnya. Kalau mengutip seloroh Gus Dur, ia termasuk orang yang gila dengan NU. Nyaris sebagian besar hidupnya beberapa tahun terakhir diabdikan diri ke NU.
Basah kuyup badannya sesampainya ia tiba di rumah yang letaknya, di desa perbukitan Banyumas bagian barat. Yah, desa yang terkenal dengan kampung penderes. Namun anak-anaknya dikenal cerdas dan banyak mewarnai prestasi di sekolah-sekolah favorit jaman dulu hingga sekarang.
Sesampai di rumah nyaris tengah malam. Ia membuka pintu, ia menyibak gorden kamar. Dilihatnya dua anak titipan almarhumah isterinya yang telah lelap dalam tidurnya. Selimutnya tersibak. Tetapi di tengah deras hujan, mereka sangat lelap. Ia mendongak ke atas langit-langit kamar. Ya, untung atap tidak bocor lagi. Alhamdulillah.
Baca Juga : Tentang Abah dan Pertanyaannya
Selama beberapa hari ini banyak peristiwa yang terjadi. Rutinitasnya ke pasar setiap pagi dijalaninya agar dapur tetap ‘ngebul’ sejak ada istri hingga istrinya meninggal dunia karena sakit keras. Ah, setiap memandang dua anaknya tidur, terlintas di pikirannya tentang perjuangan isterinya. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak sudah lumrah.
Di tengah hujan deras malam itu, ia duduk sendiri di ruang tamu. Beberapa hari lalu, sebelum ia sampai pulang ke rumah dari pasar, ia mendapati kecelakaan truk. Sebuah truk terbalik dan menabrak sebuah rumah di tepi jalan nasional Purwokerto Jakarta. Sang sopir terjepit, tanpa dinyana ia tergerak hati spontan turun dan turut serta menolong sopir itu. Ah, terluka berat, akhirnya sang sopir meninggal dunia.
‘Digedhongono dikunciono wong mati mangsa wurungo’. Jelas sekali satu larik paragraf dari syair pujian ‘Ayun ayun badan‘ yang sekarang sudah jarang terdengar dari tajug-tajug desa itu terngiang dengan jelas. Betapa nafas memang begitu singkat, namun pengharapan dan perjuangan cukup panjang bagi manusia.
Baca Juga : Lepasnya Burung Kesayangan Pak Lurah
Sambil mendengar deras dan sesekali terdengar bunyi gemuruh guntur, ingatannya kembali ke masa lalu. Sebelum ia menikah, punya anak dan menjadi ketua ormas pemuda bintang sembilan, ia ‘mondok’ di pesantren milik Abah Habib Idrus. Ia bukan apa-apa dan siapa-siapa.
***
Ia ingat benar malam itu. Ya, suatu malam sekitar pukul 23.00, semua santri pondok di kumpulkan. Jarang sekali sang guru mengumpulkan semua santri secara mendada. Tapi sebagai santri, apa yang menjadi dhawuh sang kiai, ia tak mungkin membantah. Dhawuh sang kiai wajib ditaati.
‘Kalau disuruh masuk apipun, saya harus manut kalau itu dhawuh sang kiai’. Ia ingat betul kata-kata GusDur saat hendak terpilih jadi presiden. Ya itulah ketakdziman dari sang murid kepada guru tanpa kecuali. Termasuk dirinya dan santri lain seperti ia mondok di pesantren itu.
Baca Juga : Sholawat Nabi di Sekitar Pendirian Menara….
Jelang tengah malam itu, sekitar 40 santri dikumpulkan. Sang Abah memberi wejangan kepada seluruh santri. Hingga kini ia bahkan telah lupa seluruh wejangan dari Sang Abah kecuali satu hal yang membekas hingga sekarang.
Ingatannya yang membekas itu adalah ketika sang guru di pertengahan ceramahnya bekata. “Mondhok sing mantep sopo ngerti dadi ketua Ansor,” . Entah kenapa perkataan itu terasa menancap di hati dan pemikirannya. Dan entahlah kenapa seolah waktu itu, perkataan itulah yang terdengar dengan keras seperti di depan kedua telinganya. Entah santri yang lainya.
Usai pertemuan itu, perkataan dari Sang Abah masih terasa dan teringat di kepalanya. Namun ia tak berpikir banyak lagi. Apalagi ia bukanlah termasuk santri istimewa dibanding santri lainnya yang pandai menghafal dan lancar membaca kitab waktu mondok itu.
Ia hanya seorang santri yang lebih banyak menghabiskan waktu di ndalem. Ia jarang mengaji. Seringnya malah justru mengerjakan pekerjaan rumah tangga apapun. Mulai dari urusan dapur, kamar mandi, mencuci, ngepel hingga ke kebun. Sering lagi ia harus ‘ngetan ngulon ngalor ngidul diperintah sang guru ataupun keluarga ‘ndalem’ apapun dan siapapun. Yang penting mau dan tak pernah menolak.
Meski demikian seiring dengan waktu, ia tetap menjalani aktivitasnya menjadi santri sebagaimana biasanya. Di waktu mangsa ketiga, ia bersama santri lainnya biasa mengambil air ke sungai dekat perbatasan antara kabupaten untuk kebutuhan pondoknya. Sementara setiap malam, bersama santri lainnya mereka terbiasa mendawamkan Ratib al Habsyi yang dikarang sang guru.
Ya sang guru memang secara khusus lebih banyak mengisi spiritualitas para santri dengan ritual dzikir wirid setiap malam. Soal itu, ia pun tak pernah melewatkan sebagaimana santri lainnya. Sementara saat pengajian kitab lainnya, justru ia seringkali terlewat karena berada di dapur, ataupun melakukan pekerjaan lainnya.
Tak heran setelah bertahun-tahun ‘mondok’, ia merasa masih belum bisa memantaskan diri sebagai alumni pondok usai mukim di kampung. Namun sebagaimana pesan dari sang kiai, hidup harus ‘mbanyu mili’. Upayakanlah selalu yang terbaik dan sebisa mungkin.
***
Hujan masih saja turun deras hingga tengah malam disertai gemuruh guntur. Ia kembali melongok ke kamar. Satu dari dua anaknya telah berganti posisi dengan membalik tubuhnya. Ia benarkan letak selimut hingga menutup tubuh anaknya itu.
Ia kemudian kembali ke ruang tamu dan duduk di kursi sambil menikmati malam. Ia tersenyum, tanpa dinyana ia kembali mengingat peristiwa jelang tengah malam saat sang abah mengumpulkan 40 santrinya itu. Ia geleng-geleng kepala dan kembali tersenyum sendiri. Ternyata ia telah menjadi Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor tiga periode dan kini ia sedang mendapat amanat menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang ormas pemuda yang sama. Ah perkataan sang guru berpuluh tahun kemudian itu benar-benar terbukti.* (Susanto-3)







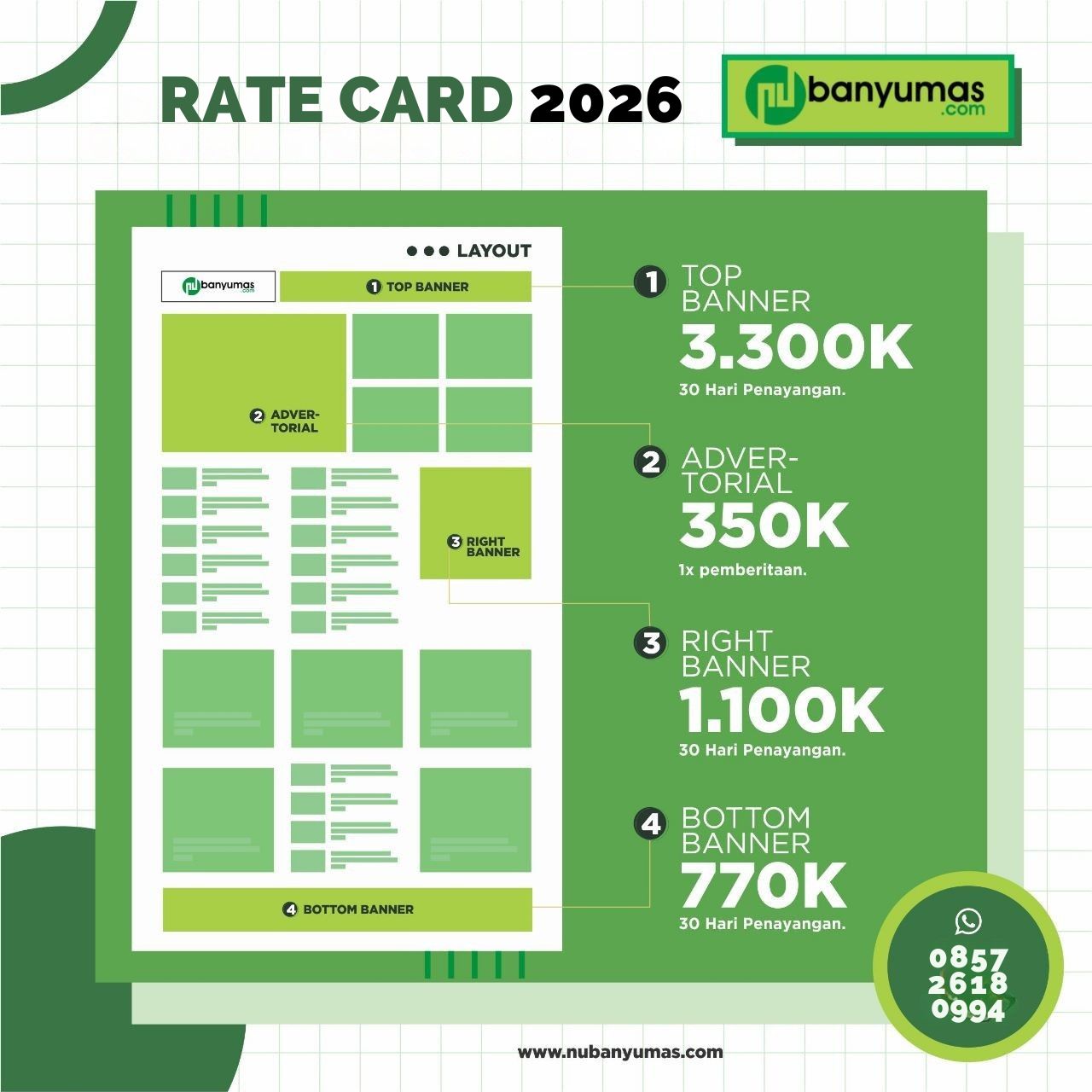







Komentar ditutup