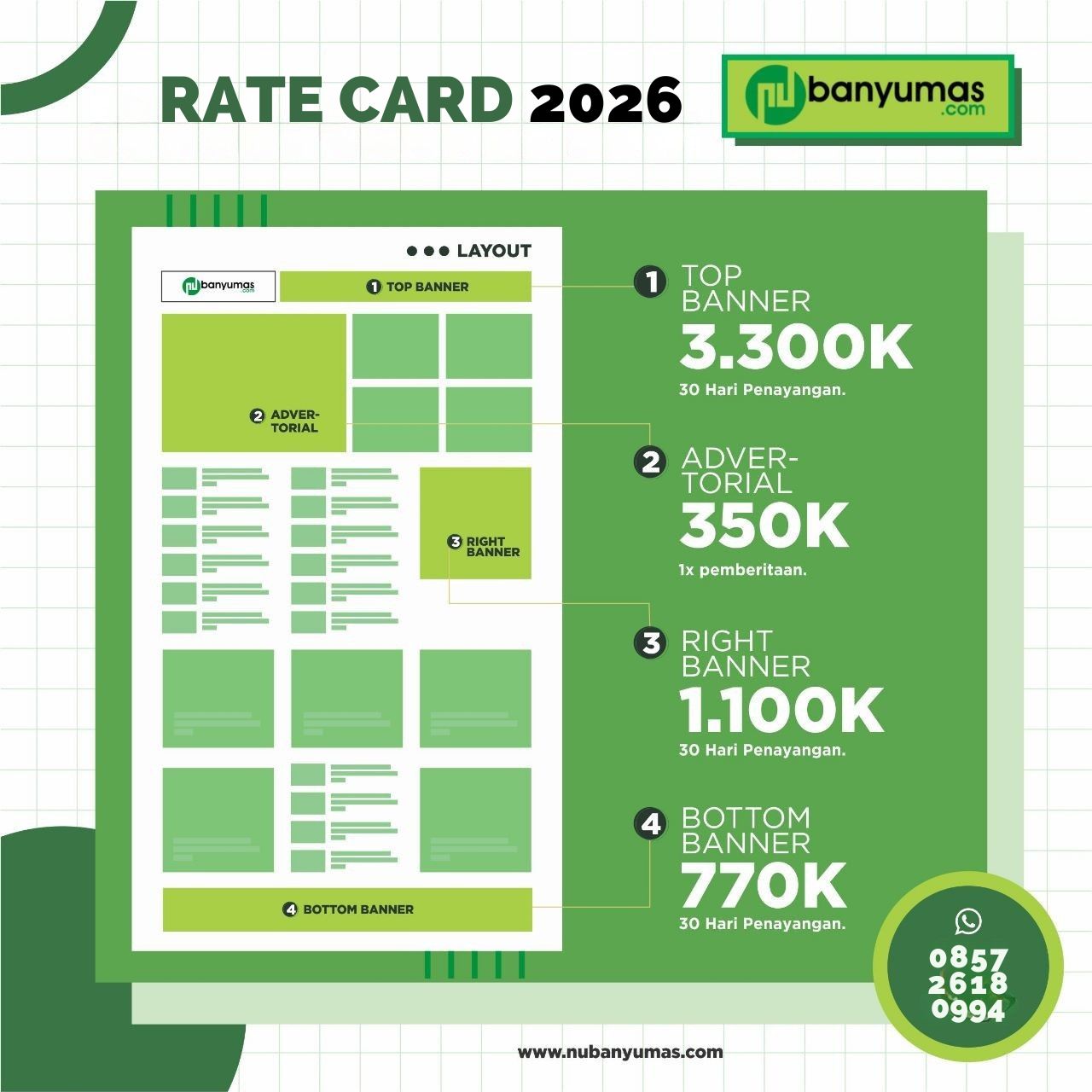KOTA PURWOKERTO Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-26 Rabiul Akhir 1365 H atau 26-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia merdeka, Kota kecil di bagian selatan Jawa Tengah ini menjadi tuan rumah Muktamar NU ke 16.
“Muktamar Nahdlatul Ulama ke-XVI diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu 26 Rabiuts Tsani 1365, bertepatan 26 hingga 29 Maret 1946,” catat M. Sholahudin dalam buku Biografi Tujuh Rais Am PBNU.
Muktamar NU di Purwokerto disebut menjadi muktamar NU yang paling fenomenal, karena pada tahun-tahun tersebut nuansa revolusi masih sangat kental dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa keputusan penting juga diputuskan saat itu, antara lain mengukuhkan kembali semangat Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan berdirinya organisasi sayap perempuan NU pertama dengan nama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM), hari ini kita kenal dengan nama Muslimat NU.
Jauh sebelum itu, pada tahun 1928-an, di Sokaraja diadakan sebuah forum pengajian khusus untuk para Kiai yang berlangsung setiap bulan sekali. Para Kiai dari berbagai pelosok Banyumas banyak sekali yang hadir dalam pengajian tersebut, tak lupa mereka juga membawa kitab-kitab seperti, Tafsir Al-Baidhowi, Kitab Hadits Al-Bukhari, Kitab Ihya Ulumuddin, Kitab Al-hikam dan kitab yang lainnya yang sudah disepakati.
Kitab-kitab itu merupakan kitab besar yang memiliki daya hidup, kalau dibaca di hadapan berpuluh-puluh kiai, semuanya membuka halaman-halaman kitab yang lagi dibaca, semua menyimak dengan amat seksama. Sedikit saja salah membacanya, misalnya “Al-hamdu” (akhiran”u”) dibaca “Al-hamda” (akhiran “a”), hoo,… hoo bisa pecah suara koor menyalahkan, serentak memberikan koreksi.
Sebab salah baca akhiran ini bisa menimbulkan kesalahan tentang makna, akhiran itu menentukan fungsi kata yang dibaca, bisa berfungsi pelaku, bisa penderita, bisa pula kata sifat dan sebagainya. Salah arti ini bisa menimbulkan konklusi yang fatal tentu saja.
“Makanya, kalau cuma “setengah kiai”, jangan coba-coba memberanikan diri membaca di muka kiai-kiai, keringat dingin bisa mengucur!” kenang KH Saefudin Zuhri pada bab awal otobiografi Guruku Orang-orang Pesantren.
KH Akhmad Syatibi, Kiai paling sepuh diantara 70-an Kiai yang hadir saat itu terpilih menjadi guru dalam pengajian khusus itu. Meskipun awalnya sempat menolak “La, la, kula mboten saged la,” Kiai Akhmad Syatibi akhirnya menerima dengan syarat didampingi oleh 4 orang Kiai lainya yaitu Kiai Raden Iskandar, Kiai Akhmad Bunyamin, Kiai Zuhdi, Kiai Mursyid.
Baca Juga : Review Singkat 9 buku Karya KH Saifuddin Zuhri
“Dengan beberapa teman aku menyelinap disana. Kehadiran anak-anak tentu saja bukan bermaksud ikut mengaji Tafsir Al-Baidhowi, itu kan kajian para Kiai. Kami datang sekedar mau menonton Kiai-kiai pada ngaji,” tulis KH Saifudin Zuhri dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren.
Setiap pengajian itu berlangsung, suasana kota kecil Sokaraja mendadak ramai karena setiap Kiai yang hadir ikut pengajian tak pernah datang sendirian, mereka selalu datang bersama 3-5 orang pengiringnya. Belum lagi warga masyarakat setempat juga ikut hadir membanjiri pengajian itu.
“Suasananya jadi seperti ada Konggres. Masyarakat bertambah hidup dan syiar islam lebih dinamis dibuatnya,” catat KH Saifuddin Zuhri masih dalam buku Guruku Orang-orang Dari Pesantren.
KH Saifuddin Zuhri adalah seorang ulama pejuang kemerdekan dan intelektual NU, dia lahir di Desa Kauman, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 1 Oktober 1919. Ayahnya H Mohammad Zuhri adalah seorang petani dan penarik dokar, ibunya Siti Saudatun adalah seorang pengrajin batik. KH Sifuddin Zuhri menikmati kehidupan masa kecilnya di Sokaraja hingga usia 17 tahun, kemudian dia memutuskan merantau ke Kota Solo untuk melanjutkan pendidikanya. (*)