“BAGAIMANA kalau kita bikin pengajian yang agak besar Bib. 10 Muharam-an,” kataku suatu malam pada sang habib di musala kecil desa di perbatasan dua kabupaten itu. Musala itu masihlah berupa dinding anyaman bambu dan kayu.
“Ya, bisa,” jawab sang habib singkat.
Setelah itulah kemudian, pengajian akbar mulai dilaksanakan di akhir tahun 1980-an. Aku, Choerul Fuadi, Imam, Dofier Syam, Tofik, Habib Muhammad dan lainnya lagi menjadi bagian dari pemuda perintis pengajian bersama warga, tokoh agama dan keluarga sang habib. Pengajian yang dikemas dalam acara haul umum itupun dilaksanakan di desa yang belum lama dialiri jaringan listrik itu.
Para pemuda mengguntingi kertas ‘marmer’ untuk membentuk huruf-huruf dan kaligrafi acara pengajian itu. Sprei milik sang habibpun dimanfaatkan sebagai background tempat menempel huruf-huruf karya santri dan pemuda perintis pengajian itu.
Warga yang ingin leluhur dan keluarganya yang telah mendahului untuk turut didoakan, turut memberikan iuran dan sodakoh. Sebagian uang sumbangan pengajian dibelikan makanan takir untuk jamaah pengajian. Maka kemudian di kompleks musala dan rumah yang di kemudian hari menjadi pesantren, mulai digelar pengajian akbar 10 Muharam.
Baca Juga : Kiai Nekat dengan Sebelas Santri
Pengajian akbar itu ramai didatangi warga setempat. Haul pertama kedua ketiga dan
seterusnya terus semakin ramai pengunjung. Background tulisan pengajian yang tadinya hanya dengan kertas meningkat menjadi dengan stereofoam yang disemprot cat pewarna dan kerlap kerlip lampu.
“Bagaimana kalau musala ini untuk Jumatan Bib,” usulku suatu saat.
“Hush, jangan!” kata sang habib singkat.
Bertahun kemudian, akhirnya rumah dan musala sederhana yang ramai kedatangan warga dan santri itupun dirintis menjadi pesantren. Lokasi itupun kemudian menjadi Masjid Nurrusulthon. Sang habib, sebagai perintis tetap rajin sowan bersilaturahmi dengan berbagai kalangan khususnya para kiai sepuh yang khos.
Aku ingat betul betapa di sejumlah kesempatan sowan kepada kiai-kiai istimewa, sang habib dimuliakan dan diperlakukan istimewa. Diketahui sang abah, Habib Ja’far juga termasuk durriyat kanjeng nabi yang sregep silaturahmi. Aku sebagai ‘pendherek’pun menjadi turut bersyukur dan senang mengikutinya.
Dari perjalanan silaturahmi-silaturahmi itulah akhirnya kukenal sosok Mbah Kiai Muzni Karangcengis, Mbah Nuh Pageraji, Mbah Malik Kedungparuk, dan lainnya. Dari kiai-kiai itulah, sang habib dilimpahi berbagai macam ilmu dan hikmah. Ah ada lagi Kiai dari Kedunglemah, Tinggarjaya dan banyak lagi yang aku sudah lupa. Mungkin karena setelah beberapa haul pengajian yang dirintis itu, aku justru pergi merantau ke berbagai kota besar hingga kukenal berbagai warna dunia.
Baca juga: Tentang Abah dan Pertanyaannya
Aku terbilang beruntung, meskipun aku dari kalangan orang biasa, tetapi aku dekat dengan keluarga mereka. Adanya organisasi putra yang sekarang menjadi organisasi pelajar Nahdliyin itulah, aku belajar banyak hal.
Selama ikut bersama sang habib, aku memang menemukan sejumlah kejadian yang membuat geleng-geleng kepala. Suatu waktu saat ke Purwokerto, tak sengaja rombongan sepeda onthel kami menerobos lampu merah. Kamipun diberhentikan polisi.
Kami dipanggil termasuk sang habib. Sementara polisi lainnya mencoba menepikan sepeda yang berada di tengah jalan. Tapi ada peristiwa aneh, saat berusaha mengangkat dan menepikan sepeda sang habib, pak polisi tak kuat mengangkat.
Beberapa kali, kami bersilaturahmi kepada para kiai sepuh yang khos, kami diperlakukan cukup istimewa. Ketika para tamu lain berada di balai depan, kami biasanya langsung dipersilakan masuk ke ruang tengah. Dan beberapa kali sayapun melihat, sang habib muda diberikan wejangan dan ilmu khusus oleh sang kiai.
Meskipun kemudian dikenal sebagai ahli hikmah aku mengenal sang habib sebagai orang yang selalu berpenampilan biasa. Namun demikian penampilan luar tentulah tak akan mempengaruhi kedalaman akhlak dan ilmu yang ia punyai. Terbukti setelah aku berpuluh tahun merantau ke ibu kota dan kembali ke desa kudapati perkembangan majelis taklim dan rintisan pesantren itupun semakin pesat.
Kudapatkan informasi, pengajian Jumat Kliwon yang diadakan pertama kalinya pada tanggal 10 Muharam 1405 H dengan pembicara KH Bashor itulah berdirilah Pondok Pesantren Roudlotul Ilmi. Setahun kemudian, tepatnya Selasa Wage malam Rabu Kliwon 10 Muharam 1406 H/24 Oktober 1985 M, KH Hisyam, Leler, Banyumas menjadi peletak batu pertama pembangunan pesantren ini.
Di awal perintisannya, atas ide dan dukungan dari para adik-adiknya termasuk Habib Abdullah yang malang melintang nyantri di Banyumas hingga Sarang Rembang, pesantren sang habib ini terus berkembang.
***
Suatu siang di saat proses pendirian pesantren itu bertahap dilaksanakan, datanglah seorang pria ke kediaman Sang Habib. Di sana kudapati percakapan di antara mereka. Terlihat dengan jelas, seorang tamu menyerahkan amplop kepada sang habib.
“Ini Bib,” jelas seorang lelaki paruh baya yang duduk di hadapan sang habib sambil menyerahkan amplop.
“Ini untuk apa?” tanya sang habib.
“Ini sumbangan saya Bib?” katanya.
“Ya, sumbangan untuk apa dan bagaimana?” kembali Habib menimpali.
“Untuk pondok atau untuk saya?” kembali sang habib menegaskan sambil tersenyum.
“Terserah Habib saja,” jawab lelaki itu dengan bahasa Jawa Kromo.
“Begini Kang, harus jelas akadnya. Ini untuk saya atau pondok. Atau setengah untuk saya atau setengah untuk pondok atau bagaimana?” timpal sang habib.
Mendengar itu sang lelaki terdiam sejenak. Dengan malu-malu, ia memandang wajah sang habib yang masih memandangnya tersenyum. Melihat sang habib tersenyum lelaki itu turut tersenyum.
“Separuh-separuh Bib. Untuk pondok dan Habib,” kata lelaki itu.
“Alhamdulillah. Saya terima sumbangan ini. Semoga menjadi amal jariyahmu Kang,” jawab sang habib sambil menyalami lelaki itu. Kemudian setelah itu sang habib seraya mengangkat tangan melangitkan doa di hadapan lelaki itu. Lelaki itupun mengamini. Begitulah sang habib, soal fiqh ia memang selalu tegas dan jelas.
Di tengah proses pembangunan pondasi salah satu bangunan pondok, sang habib juga dengan ‘entheng bokong’ melihat langsung prosesnya. Ia memastikan segala proses pembangunan pondok itu berlangsung baik dan benar.
“Kang, punten itu batu kok beda ya dengan yang lain,” katanya suatu kali kepada pekerja pembangunan pondasi.
Mendengar itu seorang santri yang turut membantu proses itu tersenyum.
Mendengar pertanyaan dari sang habib, sang santri langsung nyambung. Benarlah diketahui kalau batu yang warnanya memang bukan berasal dari pondok tersebut.
“Bener Kang. Jangan asal pasang batu. Kalau itu bukan punya kita jangan dipasang. Kembalikan ke tempat semula,” kata Sang Habib pada santrinya yang mengangkat batu sebesar kepala.
Lalu ke mana batu sebesar kepala itu dikembalikan? Tiga orang santri kemudian terlihat saling bercakap. Kemudian salah satu dari mereka menunjukkan jarinya ke suatu arah. Kemudian santri lain memanggul batu sebesar kepala itu dan berlalu pergi.
Baca juga : Sholawat Nabi di Sekitar Pendirian Menara
***
Beberapa tahun kemudian di tengah kontestasi pemilihan kepala desa, aku punya sikap berseberangan dengan sang habib. Pilihan jago kepala desa pilihanku adalah orang yang kuanggap se ideologi denganku. Sementara sang habib punya pilihan lainnya.
Apesnya, jago pilihanku malah kalah dalam pemungutan suara pemilihan lurah itu. Betapa kecewanya aku dan itupun mempengaruhi sikap dan interaksiku pada sang habib. Aku yang sejak muda bersahabat akrab dengan sang habib dan keluarganya, benar-benar putus hubungan. Jangankan menghadap ke sang habib, menapakkan kakiku di halaman pesantren itupun aku enggan.
Sampai kemudian tiga tahun berlalu, akhirnya sang lurah pilihan sang habib tersandung masalah dugaan penyimpangan. Meski akhirnya tak terbukti, namun sang lurah mengalami sakit sehingga perjalananan menapaki jabatan itupun harus pupus di tengah jalan.
“Bib, saya minta maaf,” kataku menghadap sang habib usai berhentinya jabatan sang lurah desaku.
Mendengar itu, sang habib hanya memberikan senyuman dan anggukan. Kukira ada tanggapan yang panjang terhadap hal itu. Namun hanya jawaban datar yang diterima olehku.
“Pancen kowe wong edan. Angger ora kaya kuwe ya udu kowe?” katanya sang sangat faham perangkaiku sejak kecil. Sejak kecil aku memang biasa bersama adik-adiknya di rumah sang abah Habib Ja’far al Habsyi.
Setelah itulah, perasaan mangkel yang sebelumnya memadat di pikiran dan dadaku mencair. Akupun masih mengenali sang habib seperti dulu. Seorang yang bisa dibilang tak pernah marah dengan siapapun.
Baca Juga : Pesan Ke-tiga dari Sang Habib
Sampai kemudian saatnya tiba, saat masa akhir jabatan kepala desa berakhir, aku
menghadapnya lagi. Sebelum aku berbicara soal niatan dan dukungan warga kepadaku untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, ia sudah berkata terlebih dulu.
“Sekarang yang maju kamu dulu, nanti kemudian yang lain,” katanya kepadaku. Akhirnya kumantapkan diri untuk maju dalam pemilihan orang nomor satu di desa ini.
Atas dukungan banyak warga akhirnya aku berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi pilihan lurah ini. Sayang, sang habib wafat terlebih dulu sebelum aku sowan menyandang predikatku sebagai orang nomor satu di desa ini. Ya predikat dunia yang hakikatnya tak berarti apa-apa.
Aku yakin, meski di alam sana, sang habib justru lebih awas mengawasiku dan menasihatiku.Tak terasa sudah seribu hari terlewati sejak wafatnya sang habib. Salam takdzim Bib, mohon berkahnya Bib semoga aku selamat sampai akhir jabatan. Al Fatihah. (Susanto-)







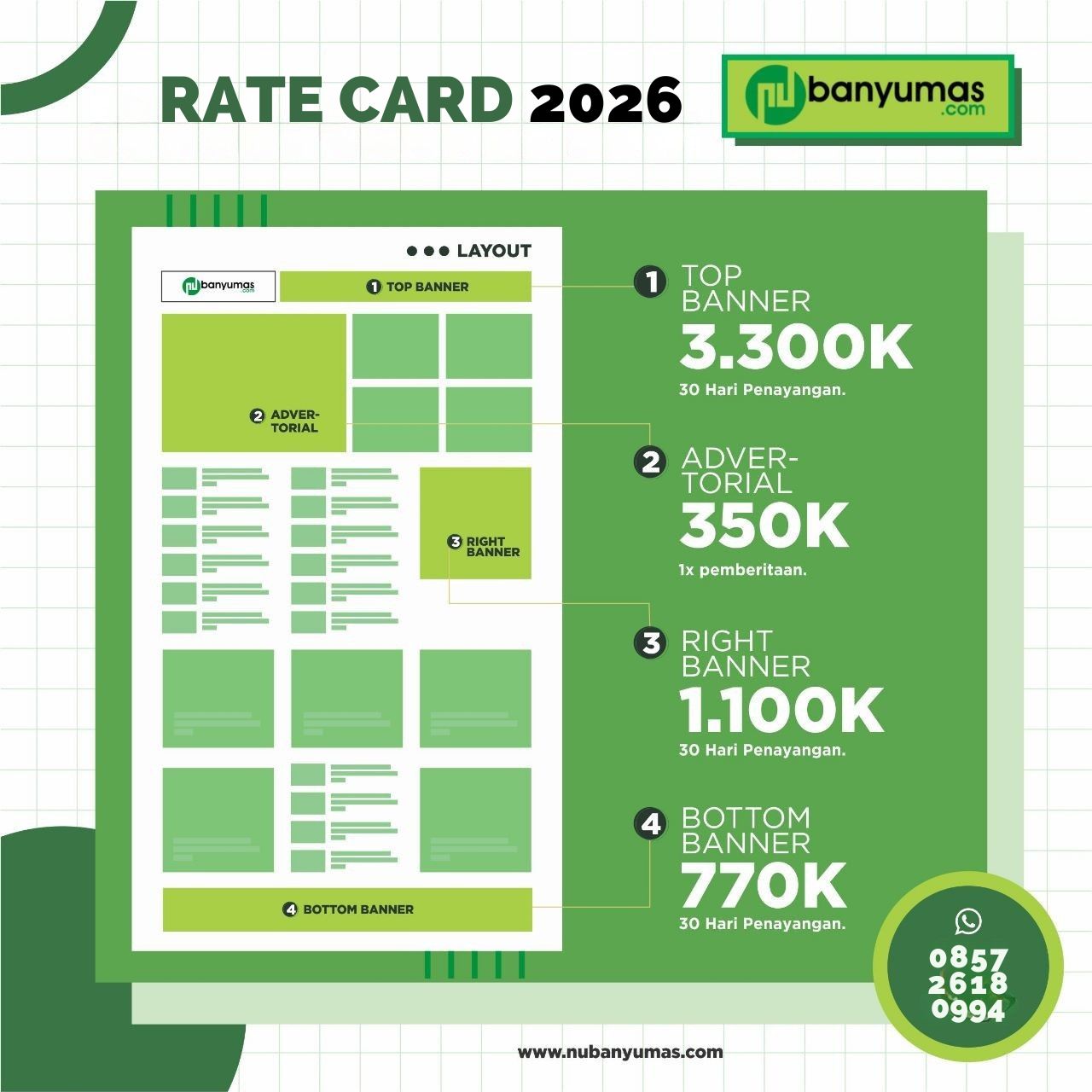







Subhanalloh barokalloh pak, saya bercengkerama dengan beliau cuma sekali di senon itupun sambil mijit beliau.