KH Abdurrahman Wahid atau akrab dengan sapaan Gus Dur merupakan Presiden Indonesia yang keempat. Masa jabatan yang hanya bertahan selama 20 bulan tersebut, diwarnai dengan gejolak dari berbagai kalangan masyarakat yang berujung pada pemakzulan saat itu.
Pada masa keemasannya, Gus Dur merupakan sosok yang eksentrik, kharismatik dan sosok yang alim, beliau menjabat sebagai ketua Tanfidziyah NU selama hampir 15 tahun. Membuktikan kapasitas, ketajaman dan ketrampilan beliau dalam membesarkan NU pada masa itu, wajar jika beliau mampu terpilih menjadi prsesiden.
Namun sayang, tepat pada tanggal 23 Juli 2001, gusdur dipaksa mundur dari jabatannya secara tidak terhormat. Padahal dengan kekuatan politik yang dimilikinya, beliau bisa saja mempertahankan kedudukannya.
Pada saat beliau menjabat, warga nahdliyin dan kalangan elit pesantren khususnya para kyai menjadi sumber kekuatan dalam konteks khazanah politik nasional untuk menjaga keseimbangan dan pemelihara keharmonisan politik. Yanto dalam disertasinya yang berjudul Dinamika Kultur Politik NU : Studi Kiai Khos pada Masa Pemerintahan Gusdur, mengutarakan hal yang sama.
Selain itu, beliau juga dikenal sebagai presiden satu satunya yang merangkul kaum minoritas, menjunjung tinggi moralitas, nilai nilai kemanusiaan, yang selalu menjadi prinsipnya dalam segala hal.
Pendapatnya seringkali terlihat tanpa tendensi politik pribadi atau kelompoknya. Ia berani berdiri di depan untuk kepentingan orang lain atau golongan lain yang diyakininya benar. Tak jarang ia seperti berlawanan dengan kelompoknya sendiri.
Bahkan semasa ia menjabat presiden, sepertinya jabatan itu tak mampu mengeremnya untuk menyatakan kebenaran yang diyakininya.
Kenyataan tersebut tidak sebanding dengan proses pemakzulan beliau sebagai presiden, Upaya pemakzulan beliau murni karena hasrat politik kelompok tertentu.
Arie Sulistyoko, dalam jurnalnya yang berjudul Pemakzulan Presiden dalam Persepsi Konstitusi (Studi Kasus Presiden Abdurrahman Wahid) menyimpulkan bahwa pemakzulan terhadap gusdur lewat Sidang Istimewa MPR di luar hukum dan konstitusi. Hal ini disebabkan, MPR hanya menggunakan TAP MPR No. III Tahun 1978 bukan menggunakan UUD 1945.
Setidaknya ada empat pelanggaran hukum yang ia paparkan dalam jurnal tersebut menyoal pemakzulan. Jadi jelas, alasan politik yang dikedepankan bukan alasan konstitusi.
Melalui sosok Gus Dur yang menjadi simbol gerakan politik NU pada masanya, NU berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Meskipun dicederai oleh kelompok ekstrem, tak ada dendam, tak ada kebencian dari warga nahdliyin atas peristiwa itu. Hanya ingatan dan catatan sejarah yang akan menunjukan.
Dua puluh tahun berlalu, pemakzulan Gus Dur dianggap melukai warga nahdliyin. Beberapa hari terakhir, media sosial saya dipenuhi dengan unggahan unggahan yang berkaitan dengan proses pemakzulan Gus Dur. Dari mulai berita, foto, video, meme dan quotes Gus Dur masa itu, uforia menggingat kembali masa Gus Dur akhirnya terbangun.
Terlebih pernyataan pernyataan beliau selepas lengser diantaranya, “Saya memaafkan, tapi saya tidak akan melupakan”, atau “Tak ada jabatan yang perlu diperjuangkan mati matian”, dan “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Kalimat kalimat itu sering beliau ucapkan ketika di ruang publik, khususnya di media. Tertanam dalam pikiran warga nahdliyin.
Secara tidak langsung ini menjadi momen untuk mengingat kembali dengan jelas, faktor dan aktor dibalik pemakzulan gusdur. Bagi warga nahdliyin ini seperti membuka luka lama, mengorek ingatan yang mengendap, namun ini juga realita kekalahan kontestasi politik. Maka pelurusan sejarah harus terus diupayakan dalam rangka mencerdaskan dan memberi kesadaran untuk kaum nahdliyin. (*)







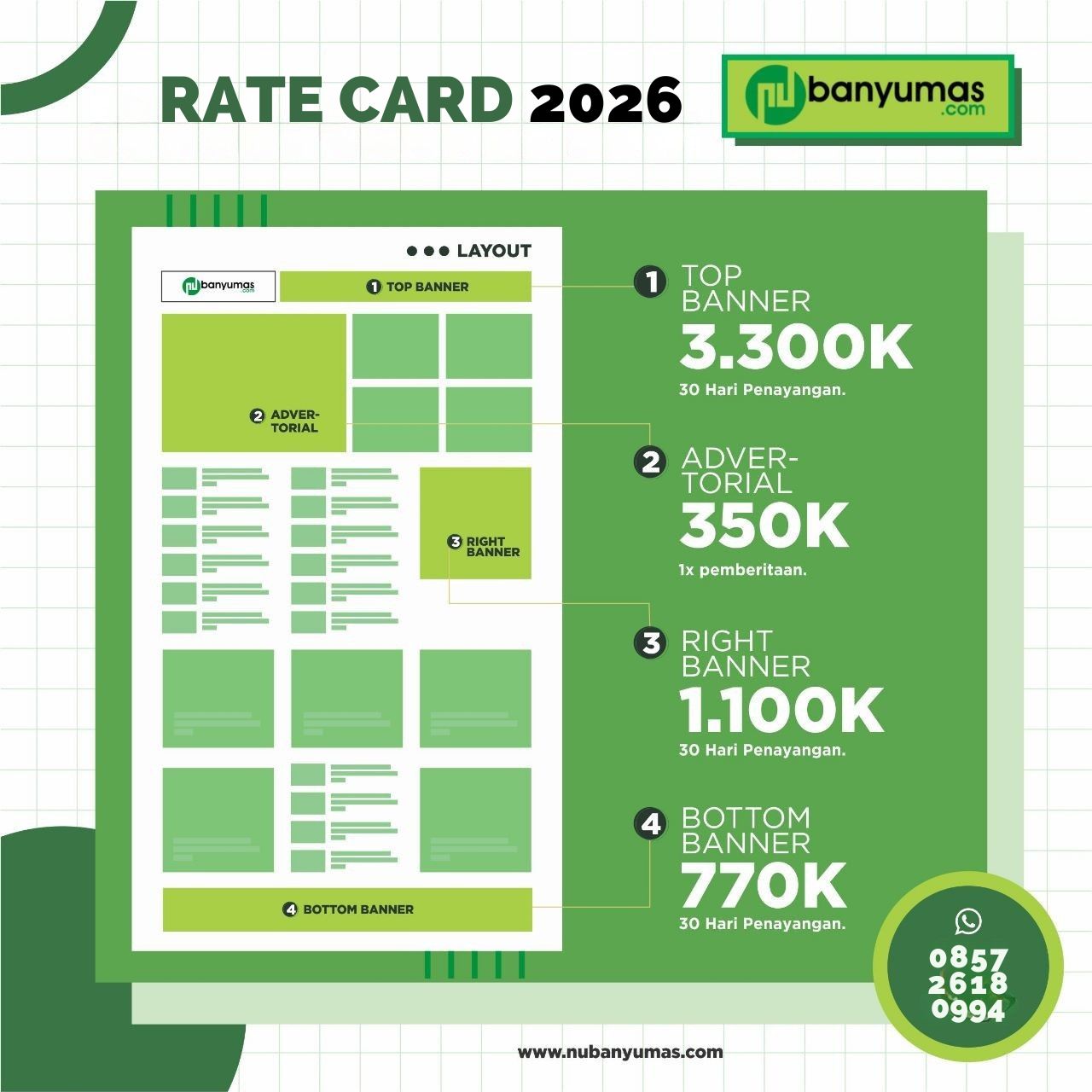







Komentar ditutup