
“KAU ingin mendirikan pondok?” kata Kiai Mustolih sambil memandang tajam sang murid yang menunduk takdzim. Meski tak melihat tatapan tajam sang guru, namun sebagai santri yang lama diasuh, sang murid merasakan kesejukan dari sang guru.
“Nggih Abah, mohon doa pangestunipun,” kata sang murid yang umurnya masih kepala dua itu. Ya, muridnya berasal dari ujung utara perbatasan dua kabupaten. Ia terbilang masuk dalam murid yang istimewa, dibandingkan murid lainnya. Meski demikian ia tak anak emaskan murid yang satu ini.
Mendengar permintaan doa dari muridnya yang belum lama mukim di tempat tinggalnya sendiri, sang kiai hanya tersenyum. Sementara sang murid sambil tertunduk dan bersila masih duduk penasaran menunggu jawaban sang guru soal permintaan doa restunya mendirikan pesantren itu.
“Ya, aku restui dirimu untuk mendirikan pesantren. Namun ingat, jumlah muridmu nanti akan tetap berjumlah 11 santri saja,” kata sang guru sambil tersenyum.
Mendengar itu, mantaplah sang murid. Meski demikian semburat tanya bercokol di benaknya mendengar perkataan jumlah santri yang selalu 11 tersebut. Ah, entahlah, yang penting niat dan tekadnya untuk mendirikan pesantren di kampungnya telah mantap. Apapun yang terjadi, maka itu soal nanti. Yang paling penting adalah restu sang kiai telah didapatkannya.
###
Peristiwa hari permohonan restu itu telah berlalu sekian tahun dan masih diingat oleh Idrus. Rasanya pertanyaan dan peristiwa itu baru kemarin terjadi. Namun peristiwa itu selalu membekas di pikiranya dan di hatinya. Apalagi ketika lelaki berperawakan tinggi besar dengan jambang dan jenggot tebal itu sedang mulai memberikan pelajaran agama di depan muridnya.
Sambil memandang murid-muridnya yang sedang menghafal nadzoman dan hafalan pelajaran lainnya, ia seringkali tersenyum sendiri. Benar pula apa kata sang guru, dari tahun ke tahun tetap saja muridnya selalu berjumlah 11 santri saja. Ya, ketika tambah murid baru, maka akan keluar murid lainnya. Selalu saja begitu, sehingga jumlah muridnya tetap saja berjumlah 11 orang.
Entahlah, apa maksud dari sang guru kenapa jumlah bilangan santri yang mondok di pesantrennya itu hanya 11 orang saja. Apa makna 11 baginya, bagi gurunya. Namun memang jumlah bilangan tentulah tak harus dipikirkannya. Bukankah, tidak semuanya harus dipikirkan atau dimasukkan ke dalam logika manusia.
Sebagai seorang santri, tugasnya adalah bagaimana takdzim dan menurut apa yang didhawuhkan oleh sang guru. Meski harus terjun ke apipun, kalau itu perintah sang guru ia akan manut, menurut. Karena dari sang gurulah setiap berkah, keramat dan keselamatan akan didapatkannya. Pelajaran dari Kitab Ta’limul Muta’alim tentang adab dan keutamaan menuntut ilmu kepada sang guru itupun diberikan kepada murid-muridnya. Ya, santri yang selalu berjumlah 11 orang ini.
Ya, dengan jumlah santri yang berjumlah 11 orang inilah, kegiatan pesantren ini terus berjalan. Dengan modal keyakinan kepada Alloh SWT, ia mulai membangun langgar kecil di samping rumahnya. Sementara asrama untuk santrinyapun dibangun tak jauh dari langgar kecil yang kelak akan menjadi masjid.
Iapun tak mempedulikan apa kata orang di sekitarnya ataupun teman-teman santrinya sewaktu ‘mondhok’ yang menyatakan dirinya sebagai Kiai Nekat. Ya, memang sejak dulu ia selalu dikenal sebagai orang yang terlebih dulu bertindak. Sementara orang lain akan mempertimbangkan dulu tindakannya. Padahal baginya yang telah menjadi pertimbangannya adalah keyakinannya kepada Alloh dan sebenarnya ia telah berpikir matang.
Baca Juga : Doktor Ridwan : Koin NU Itu Sebenarnya…
Tak terasa putri sulungnya telah merampungkan pendidikanya di pesantren tempat dulu mondok. Meski perempuan, namun putri sulungnya ini terbilang cukup cekatan, lincah dan berani. Maka selesainya sang putri sulung dari pendidikannya di pesantren kabupaten selatan Jawa ini menjadi tumpuan harapannya.
“Cah, kamu pimpin pondok ini. Abah percaya padamu,” katanya pada putri sulungnya yang dua nama di belakangnya ia ambilkan dari sufi perempuan Rabiatul Al Adawiyah.
Putri sulungnya yang mendengar itu hanya terdiam sejenak dan memandang Abahnya seperti tak percaya. Namun dengan mata tajam dan tersenyum seperti tanpa beban, putri sulungnya itu mengiyakan apa kata Abahnya.
“Nggih Bah,” kata putri sulungnya itu sambil berlalu. Sang putri yang bermata bulat dan berhidung mbangir itu langsung berlalu sambil memeluk sejumlah kitab kuning. Usai mencium tangan Abahnya, ia tinggalkan sang Abah. Iapun berlalu, sambil berjalan cepat. Meski perempuan, namun ia terbilang lebih cepat. Setelah beberapa langkah berjalan, ia menoleh kepada Abahnya sambil tersenyum lebar. Abahnya hanya mengangguk tersenyum dan geleng-geleng kepala.
Ya, konon sejak itulah, sejak ijab qobul ‘pasrah’ sang Abah kepada putri sulungnya itu, perubahan pondok utamanya soal 11 santri mulai terlihat. Ah, entah kebetulan atau kebenaran, namun hal itu kemudian menjadi cerita bersambung dari mulut ke mulut pengurus pondok dan santri kemudian.
Sejak itulah pesantren yang berada di perbatasan itu mulai menerima santri perempuan dengan pelajaran yang banyak juga diberikan oleh putri sulungnya. Ya, pesantren itu tidak lagi berjumlah sebelas orang saja. Jumlah santri di pondok itu bertambah dari tahun ke tahun. Maka dengan ikhtiar melalui campur tangan sang putri sulung itu, pesantren mulai berkembang bahkan kemudian mendirikan Madrasah Tsanawiyah yang diperuntukkan untuk santrinya.
###
Di suatu sore yang cerah, sang Abah duduk di kursi ndalemnya, sayup-sayup ia mendengarkan putrinya yang telah mengajar dari bilik pesantren. Usai menyeruput kopi kental buatanya uminya anak-anaknya ia menghembuskan asap rokok kretek yang dinyalakannya sejak tadi. Ia tersenyum sambil mengingat apa kata dari sang guru. Dalam pikirannya ia tak bisa menampik kalau jumlah santri di pesantrennya telah berjumlah ratusan santri. Namun ia juga tetap membenarkan kalau hakikatnya santri yang ia asuh sejak pertama kali adalah 11 orang saja. Selebihnya dari itu adalah santri dari putri sulungnya.
Sambil merenungi hal itu, ia kembali menyeruput kopi pahitnya. Sementara itu sang isteri melintas. Perutnya mulai membesar, anaknya yang kesekian sebentar lagi akan lahir. Perempuan itu melintas sambil menggandeng salah satu putranya menuju ke dalam rumah.
“Kenapa Bah, kok senyum-senyum sendiri?” kata sang isteri, perempuan pilihannya yang merupakan saudara dari teman karib ‘mondoknya’ asal Tegal.
Mendengar itu ia hanya tersenyum. Di matanya terlintas beberapa peristiwa yang membuatnya sering geleng-geleng kepala. Soal permintaan ijin restu mendirikan pesantren kepada sang kiai hingga kebenaran jumlah santri yang selalu terbilang 11 saja.
“Ya, Tuhan, beginikah sebercandanya Engkau kepadaku,” pikirnya sebelum kemudian ia bangkit usai mendengar lantunan adzan magrib dari langgar di samping rumahnya itu.
(Susanto)






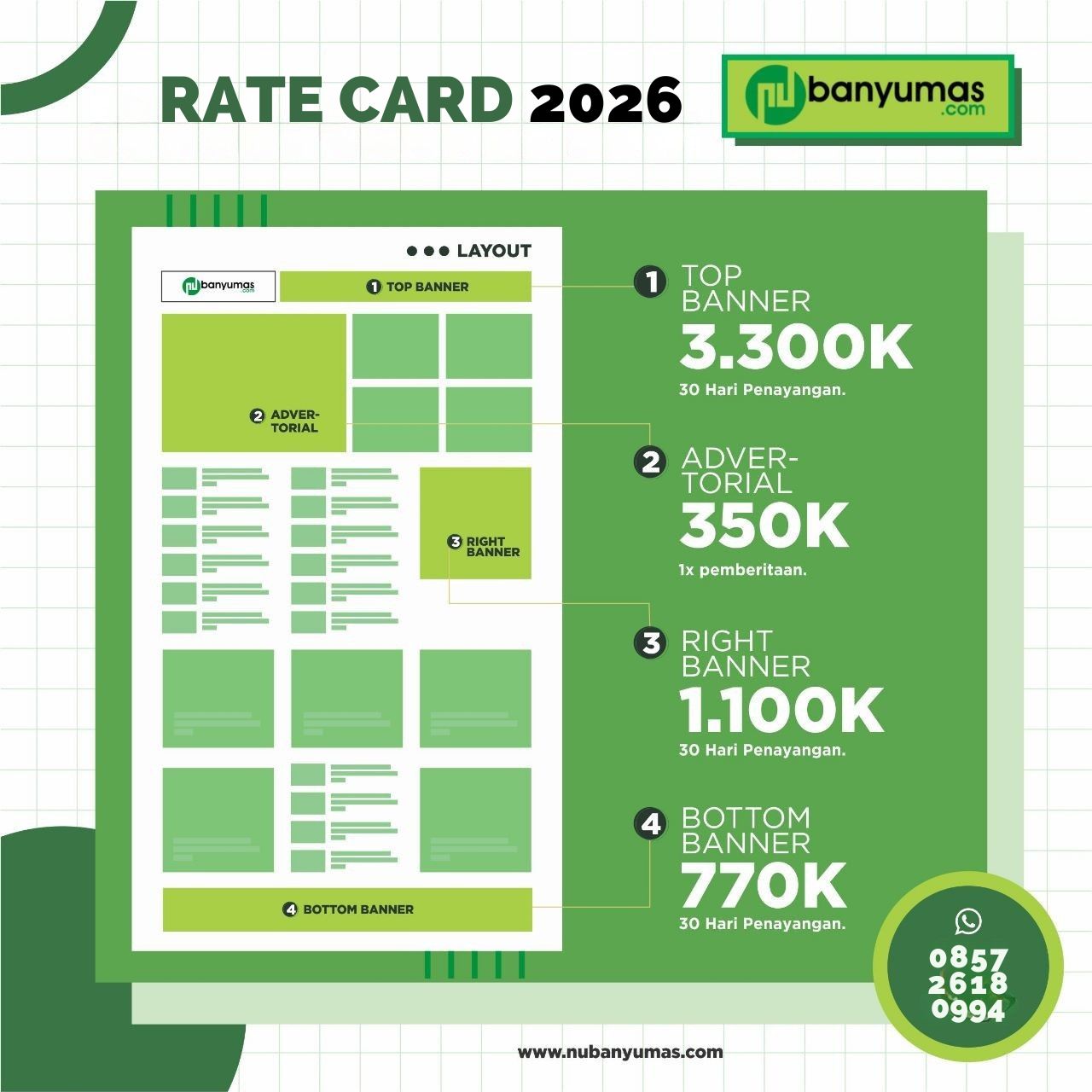







Komentar ditutup