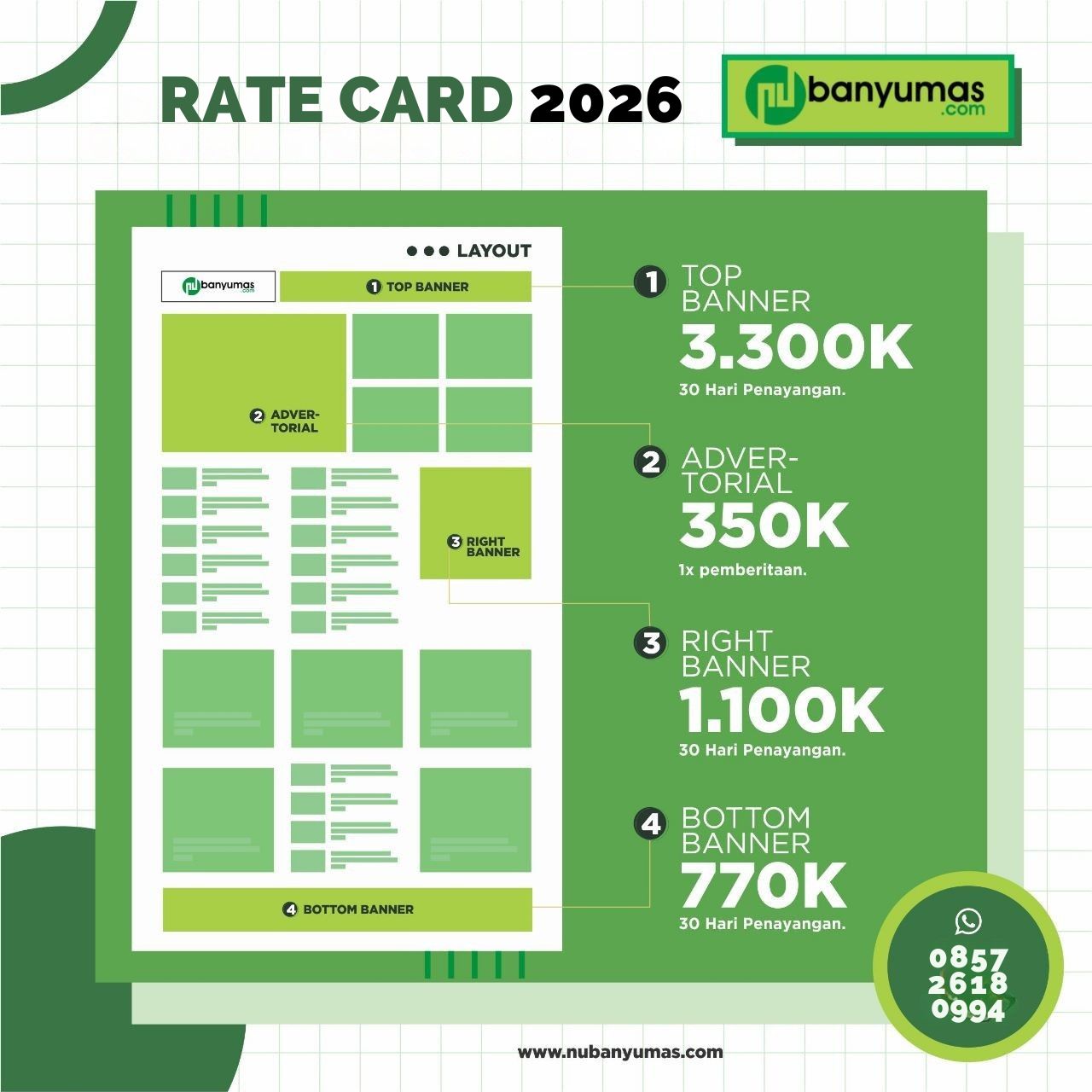KH Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, pernah menyebutkan bahwa ketimpangan dalam wawasan pengabdian NU berakar pada seluk-beluk kewargaannya.
NU tidak memiliki sistem keanggotaan terdaftar. Tidak juga ada prasyarat-prasyarat yang dilembagakan secara resmi bagi kualifikasi keanggotaannya. Maka, apakah seseorang adalah anggota NU atau bukan, lebih tergantung pada perasaan masing-masing.
Tidak adanya identifikasi yang jelas tentang kewargaan NU sebagai subyek sosial secara otomatis akan mengakibatkan sulitnya mengidentifikasi kepentingan warganya.
Di dalam masyarakat umum yang heterogen, keberadaan warga Nahdlatul Ulama pun tidak menghadirkan kategori sosial apa pun.
Maka dari itu, ketika timbul sejumlah pertanyaan tentang kepentingan sosial-ekonomi warga NU, misalnya, kita akan kesulitan mengidentifikasi subyeknya. Kalau subyeknya tidak diketahui, bagaimana mungkin menyimpulkan kepentingannya?
Pernyataan-pernyataan bahwa penduduk miskin itu orang NU, petani itu NU, yang tingkat pendidikannya rendah orang NU, yang terpinggirkan orang NU, dan semacamnya, lebih merupakan prasangka-prasangka belaka.
Bahwa kemudian secara de facto, iya, banyak warga yang NU memang terpinggirkan, miskin, pendidikannya rendah, dan sebagainya, itu tidak bisa dikategorikan dalam skup warga NU begitu saja, karena tidak adanya indentifikasi subyek dalam kewargaan NU. Sehingga kurang pas kalau dikatakan demikian itu. Paling mentok tetap diikutkan dalam skup yang spektrumnya lebih luas yaitu warga negara yang masih miskin, berpendidikan rendah, dan seterusnya dan sebagainya.
Baca Juga : Karena Saya NU, Saya Menulis Ronggeng Dukuh Paruk
Karena ketidakjelasan kewargaan NU dalam kelas sosial itu lah, maka satu-satunya yang masuk akal untuk dipersepsikan sebagai dasar kepentingan NU adalah identitas keagamaannya, yakni Islam berikut embel-embel madzhabnya, yang dalam tataran sosial jelas lebih berfungsi simbolik ketimbang operasional.
Maka, wajar apabila segala artikulasi dan gerak-gerik NU hanya beredar diseputar identitas simbolik tersebut. Bahkan proyek-proyek yang diklaim sebagai wujud pengabdian sosial pun terbit dari motivasi menghadirkan identitas simbolik, dengan orientasi yang kurang-lebih supremasis.
Hal inilah yang pada gilirannya nanti terutama dalam gejala aktivismenya, NU hanya akan dimanfaatkan sebagai alat klaim dukungan kontestasi politik di daerah atau tempat yang budaya NU-nya kuat.
Sebaliknya, di daerah yang NU-nya kurang kuat, maka para aktivis dan pengurusnya akan mengalami kesulitan untuk mau berbuat apa, dan mau bagaimana, karena tidak mengenali warganya apalagi untuk kemudian memobilisasi warganya.
Kalau NU mau melakukan transformasi bagi warganya, paling tidak harus mulai membuat kerangka untuk mengidentifikasi subyek. Ketika identifikasi subyek sudah bisa dilakukan, maka akan bisa menemukan variabel-variabel tentang apa saja sebenarnya yang menjadi kepentingannya.
Untuk melakukan itu semua, dibutuhkan kerja bersama dalam visi yang sama, terutama bagi pengurus dan aktivis NU. Ini mungkin bisa kita awali dari ngopi bersama terlebih dahulu. (*)
Abdullah Mukti
Mahasiswa Semester 3 Fakultas Sosial dan Humaniora Prodi Hukum Syariah UNU Purwokerto.