PEKAN lalu saya dikabari, kalau ayah dari rekan kerja meninggal dunia. Ya, paginya kami berangkat ke lokasi. Ke sebuah desa pinggir, perbatasan kabupaten di selatan Jawa. Ya, meski telah ada GPS atau peta digital, namun ternyata lokasi rumah tak semudah dilacak oleh kami. Apalagi medan desa ternyata naik turun, macam lagu Ninja Hatori lah.
Maka kamipun tak lagi bertanya pada Google. Teknologi terbukti tak selalu bisa diandalkan. Apalagi rekan kerja yang sedang berduka itupun tentu sedang sibuk mengurus upacara pemakaman dan lainnya. Jadi tak etis lah ketika kami menghubunginya. Apalagi ini kali kedua ke desanya, pertama ketika ia menikah. Itupun ternyata lokasinya berada di tempat isterinya.
Maka kami menyadari betapa, di tengah situasi tertentu, ada batas kemampuan jangkau teknologi. Maka kami turun dari mobil dan menemui warga desa. Ya, kami turun untuk bertanya alamat secara lisan seperti kebiasaan di masa sebelum ungkapan ‘Ok Google’ terbiasa terdengar di kuping kita.
Setelah menemui, seorang warga tepatnya pemilik warung akhirnya salah satu dari kami bertanya. Ya, ada rasa beda tersendiri, ketika yang ditanya adalah manusia bukan teknologi. Ya setelah ditunjukan arah akhirnya kami menemukan alamat yang dituju.
Sebuah rumah di tepi jalan kabupaten dengan medan menanjak. Untuk parkir memutar balikpun kami harus mencari lokasi yang luas, dan di desa ini sungguh sulit menemukan itu. Apalagi di kanan kiri jalan terbilang ada lembah curam dan jurang. Kami ‘gedhek-gedhek’ kepala. Betapa kenyataan perbedaan (pemerataan pembangunan) desa dan kota ternyata masih ada.
Sesampainya di lokasi kami mengucap salam. Jenasah sudah diberangkatkan, dan kondisi rumah duka hanya ada beberapa orang mayoritas ibu-ibu termasuk ibu dan bibi rekan kerja saya yang berduka.
“Mangga mas mba. Silakan duduk. Temannya Fulan ya,” katanya kepada kami. Betapa ramah orang-orang desa ini.
Tak beberapa lama kemudian, kami duduk di kursi-kursi yang sudah disiapkan. Halaman rumah beratap ‘embak-embak kalong‘ itu sudah tertutup tratag dadakan. Ya, bisa dilihat tratag itu dibuat sengaja setelah ada kabar duka ‘lelayu’. Dari strukturnya terlihat, tratag dadakan itu dibuat dari tian-tiang bambu yang sengaja dibuat baru. Ya, bambu bukan tiang besi sebagaimana tratag pernikahan yang jamak dipakai di kota.
Tratag yang memenuhi halaman ukuran 6×7 meter itupun tak seberapa tinggi, bisa ditaksir kurang dari 2 meter bahkan. Saya membayangkan betapa guyubnya orang-orang tempat tinggal rekan kerja kami itu. Bisa dibayangkan mereka gotong royong mencari bambu, membuat tali dan memasang tratag dadakan ini.
Disuguh Minuman
Belum selesai saya berpikir mereka gotong royong membangun tratag gratisan, kami telah disuguh dengan berpiring-piring buah, kacang, hingga mendhoan (makanan khas Banyumas) .
Ya, tradisi orang desa memang selalu ‘kober‘ (rela menyempatkan diri) di tengah situasi berdukapun. Memuliakan tamu selalu menjadi yang utama, meski sering dianggap sebagian orang sebagai pemborosan, mubadzir, merepotkan saja, jadi tak perlulah dilaksanakan. Tradisi itu yang mulai jarang ditemui di perkotaan.
Baca Juga : Penjagaan Gereja Oleh Banser
Tak lama setelah air putih gelas dihidangkan, datanglah pula senampan berisi gelas-gelas kopi panas. Kami masih merasakan aroma kopi yang menguar dari gelas-gelas panas itu.
“Ah, di tengah suasana duka masih sempat-sempatnya mereka membuat hidangan,” pikirku dalam batin. Ya bagi kami tentu merepotkan. Tapi bagi mereka ini sudah menjadi hal biasa. Ya, aku sedikit banyak merasakan itu waktu kecil, namun semakin besar di lingkungan sekarang, rasanya tradisi orang desa dan suasana itu sudah semakin hilang.
Ah, beruntunglah jadi dan berada di tengah-tengah orang-orang desa yang masih menjaga tradisi ini. Sambil menikmati kopi yang disuguhkan, sejumlah orang pulang dari pemakaman. Bertemu dengan kami, merekapun menebar senyum dan selalu mempersilakan ‘mangga-mangga disambi wedangnya‘.
Seorang kakek tua mendekati tempat kami duduk, dan mohon ijin mengambil satu gelas kopi yang masih ‘nganggur’. Tak berapa lama kemudian, ia sudah bertanya siapa kami dan dari mana. Setelah kami jawab, ia mengiyakan dan tersenyum sambil mempersilakan dan seolah berbicara ‘anggap saja rumah sendiri’. Ia pun tanpa segan meminjam korek api salah satu dari kami, untuk menyalakan rokok kretek nya. Setelah itulah, aku melihat pemandangan pipinya memeyot saat menyedot asap rokok yang digamitnya dengan dua jarinya.
Tak berapa lama, setelah orang-orang pulang dari pemakaman termasuk rekan kerjaku, para ibu keluar dari rumah sambil membawa setumpukan piring dan bakul berisi nasi dan piring-piring lauk. Maka sejumlah orang langsung mengambil piring-piring itu untuk makan bersama. Ya, beberapa orang memandang ke arah kami dan mengajak kami untuk makan bersama, termasuk rekan kerja kami.
“Jauh-jauh ke sini, masa nggak merasakan nasi sini. Sayang lho, ayo makan bersama, ” jelas rekan kerjaku yang begitu akrab dan masih mengintimi tradisi orang desa. Ya, bukankah rasa nasi sama, tetapi memang itu bukan rasa nasi, tapi ini adalah keakraban.
Sayang, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat kami akhirnya berpamitan dan mengucapkan duka cita bela sungkawa. Dan rekan kerja Si Fulan dan isterinya dan anaknya yang masih tiga tahun seperti merengek-rengek agar kami mau makan di sana. Tapi sayang dan benar-benar sayang kami tak bisa makan di sana. Mungkin itu mengecewakan mereka. Maaf, begitu kataku dalam hati. Padahal kami ingin makan sebenarnya.
Kami rindu situasi seperti ini. Tapi dengan keegoisan kami yang sok kota, kami terpaksa harus pamit terlebih dulu. Ya, alasannya kerja. Padahal alasan kerja tiada habisnya, dan seperti seolah menjadi terpenting di atas segalanya, termasuk keluarga.
Ya, ‘kepungan‘, istilah lain dari kenduri, masih populer di masyarakat pedesaan Tradisi makan bersama ini masih terjaga di setiap kesempatan. Makan bersama sebelum atau seusai kegiatan terbukti telah menguatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Orang-orang (di) desa masih percaya kalau ‘pager tai, lewih kuwat tinimbang pager wesi’.
Betapa keakraban kekeluargaan dan gotong royong memang terbukti menguatkan, memanusiakan manusia, meskipun sering dianggap merepotkan tak perlu, bahkan pemborosan oleh kalangan tertentu termasuk kita yang menganggap orang kota dan merasa paling beradab.
Betapa efektif dan efisien mungkin jadi rumus yang sangat rasional bagi yang berpikir dan merasa modern, tetapi hal itulah tidaklah selalu tepat untuk menguatkan rasa manusia. Ya, sesekali kembalilah ke desa, atau kembalilah menjadi orang desa meski berada di kota. *







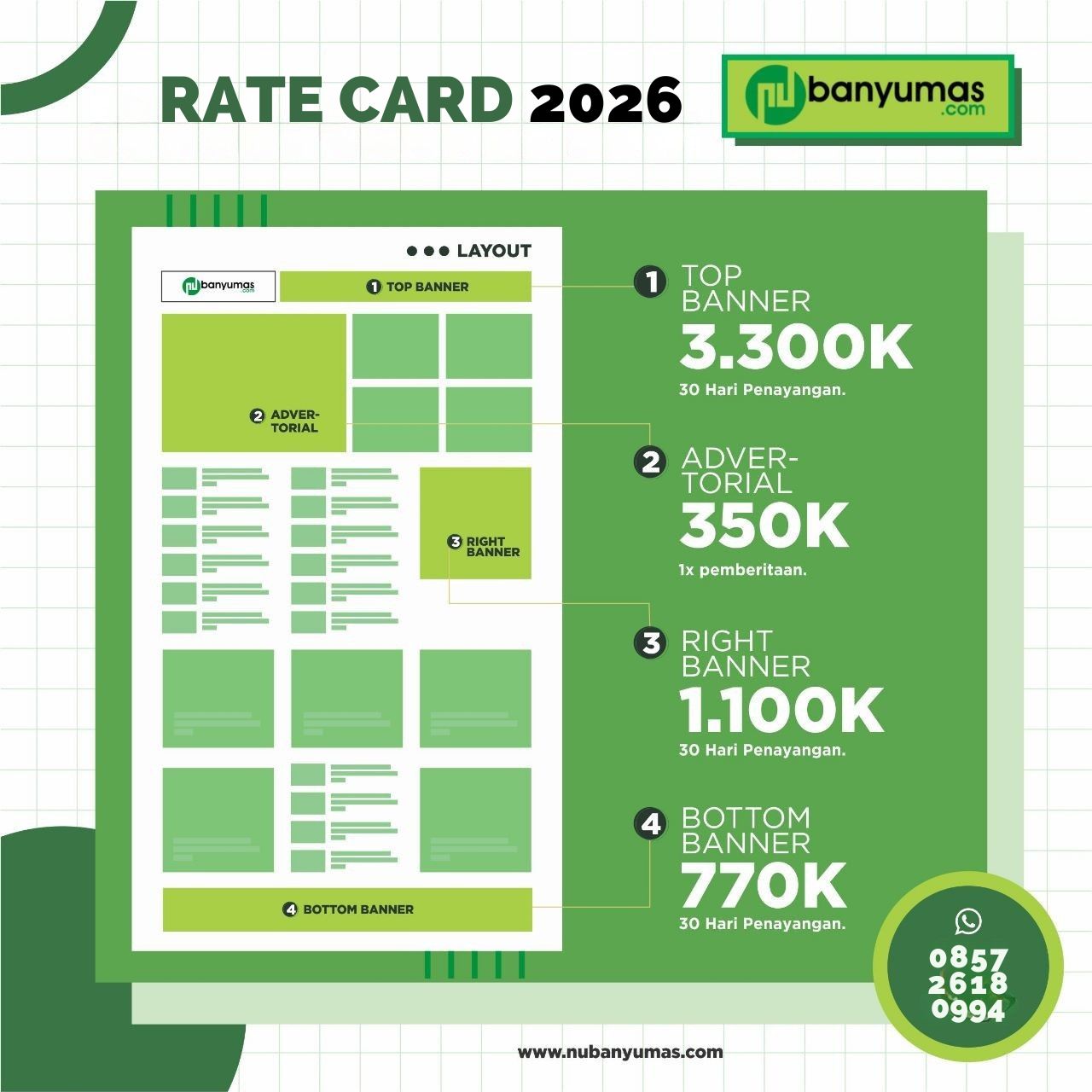







Komentar ditutup