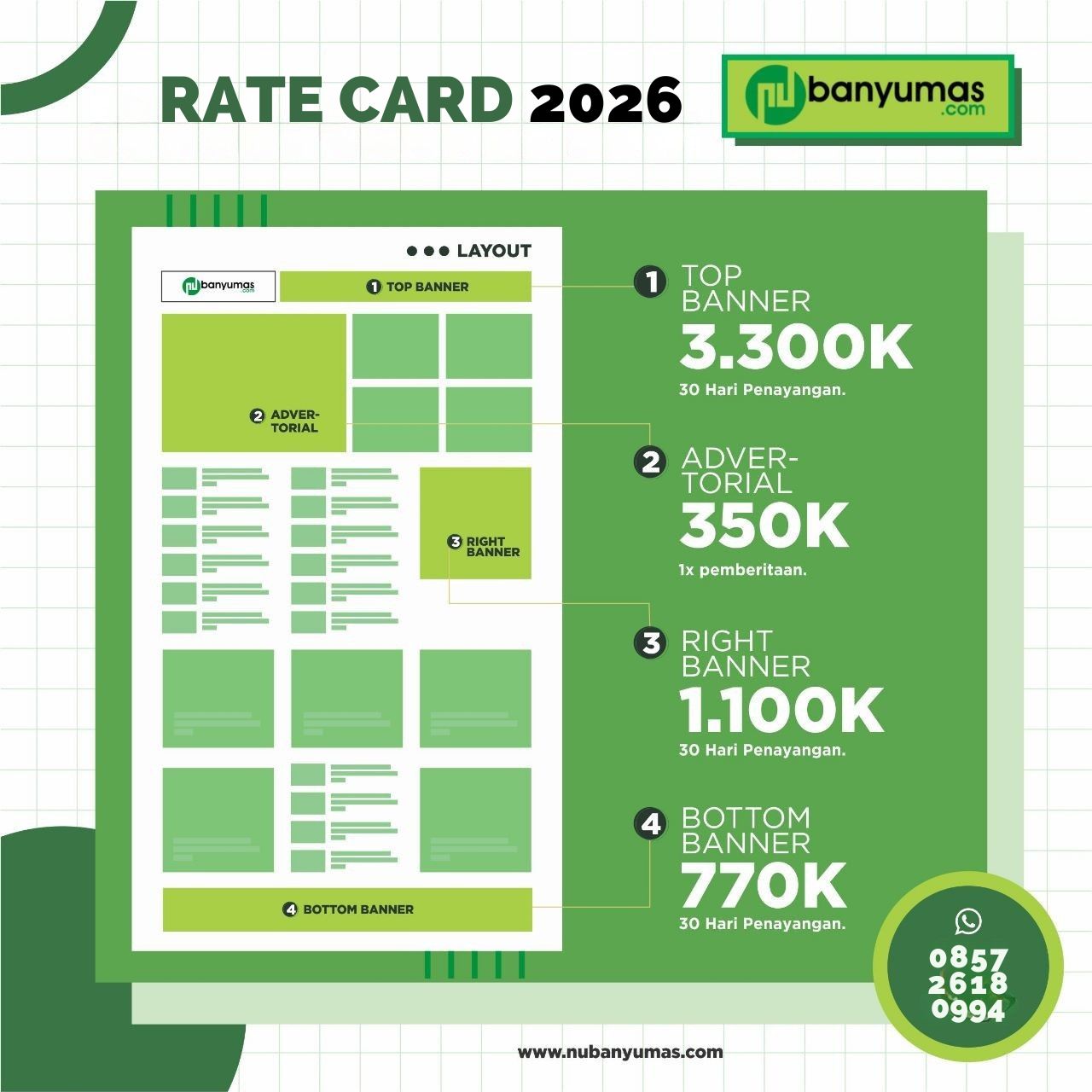“KASIHAN sekali, terlahir sudah jadi Arab,” begitulah gurauanku yang sangat rasis kusampaikan kepada Ipe Iis, sewaktu forum bedah buku pertamaku di pesantren itu. Ya, bagi sebagian banyak orang mungkin gurauanku sangat tidak lucu. Namun sewaktu di pantura tempat aku bekerja, hal itu sudah jadi biasa. Gurauan yang bernada SARA ini justru malah menjadi penambah dan penanda keakraban kami.
Kalau dipikir gurauan itu sebenarnya justru berbalik pada diriku sendiri yang merupakan seorang Jawa. Ah, meskipun banyak pro kontra tentang keunggulan ras, namun diriku mengakui kalau keturunan Ngarobi, di beberapa hal punya keunggulan tersendiri dibanding aku. Dari segi fisik saja, aku kalah dari mereka, kalah tinggi. Apalagi kalau bicara nasab, saya sungguh tidak apa-apanya dari mereka yang disebut-sebut punya garis darah tersambung pada Kanjeng Nabi.
Keakrabanku dengan si Ipe ini lebih kental ketika momen pemilihan calon legislatif tahun lalu. Kalau dilihat dari segi umur, saya lebih pas menjadi pamannya. Namun entah kenapa, kami lebih akrab. Apalagi si Ipe ini memang sangat supel bergaul. Selain modal nasab, kepandaian bergaul dan dukungan warga menjadikannya berhasil dalam kontestasi wakil rakyat itu. Sementara aku belum beruntung karena masih belum berhasil, untuk tak menyebut gagal dalam kontestasi pemilihan dewan rakyat itu.
Kini di tengah kesibukanku menjadi pemimpin redaksi media online, aku diberi kesempatan oleh yuniorku, sebutlah begitu untuk bedah buku berisi tulisanku di masa aku masih cupu yang telah menjadi buku. Tulisan yang bernada serius, motivasi dan selalu menyampaikan pesan moral sebagai sisipan isi dari Buletin Al Mudawamah yang digawangi oleh putera kiai yang terkenal cerdas di kalangan santri dan kiai di kabupaten ini.
“Saya tidak berencana sewaktu saya menulis artikel-artikel di buletin Al Mudawamah ini
menjadi buku. Ini kerja keras Doni yang mengumpulkan tulisan-tulisan di buletin Al
Mudawamah yang beredar lebih dari dua puluhan tahun lalu,” begitulah aku mengulang-ulang pernyataan menjawab pertanyaan yang sama soal proses kreatifku menulis.
Meskipun dicetak secara indie tetapi penerbitan buku ini cukup lumayan untuk menjaga eksistensi dan mengasah intelektualku. Mungkin benar juga kata sastrawan berambut gondrong putih itu betapa sastra punya keunggulan tersendiri dibandingkan jurnalisme.
“Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Kalau jurnalistik itu mendasarkan
diri pada fakta dan kendalanya adalah mulai dari ekonomi, politik, budaya. Maka sastra
kendalanya adalah kejujuran. Seberapa kita jujur dalam menulis dan apa yang kita tulis
Itulah tantanganya,” kataku menambahi pernyataan di sesi bedah bukuku.
***
Gagal menjadi wakil rakyat aku kembali menekuni duniaku; jurnalistik. Setelah lama
menganggur, akhirnya aku terima tawaran menjadi awak media online di kabupaten
wilayah Pantura itu. Awalnya aku tak percaya, apalagi yang meneleponku adalah mantan anak buahku saat aku jaya-jayanya menjadi pemimpin harian di pantura tahun
2000-an silam.
Di masa peralihan yang tak pasti, aku menganggap hanya orang bodoh saja yang mau berspekulasi untuk terjun dan mendirikan media. Makanya ketika ditelepon aku merasa
tak percaya. Namun beberapa kali ditelepon akhirnya aku pergi juga ke pantura itu. Betapa kagetnya ketika kudapati mantan anak buahku telah menjadi milyarder.
Rupanya mantan wartawan ini cukup jeli melihat peluang hingga akhirnya ia berhasil
meraup keuntungan dari proyek nasional tol di wilayah Pantura. Setelah kerja kerasnya bertahun-tahun, momen itu menjadi ledakan kesuksesannya sebagai kontraktor pembangunan. Ia telah memiliki kafe besar di pusat kota. Selain itu ia juga punya lembaga konsultan sekaligus swadaya masyarakat sebagai pemantau implementasi kebijakan publik di sana.
“Kalau mau bikin perusahaan media online sekarang ini paling tidak butuh 2-3 tahun
untuk bakar uang. Siap atau tidak soal itu,” kataku menegaskan. Apalagi mendirikan
media di saat situasi era disrupsi sekarang ini tidak boleh main-main. Sudah banyak
media yang gulung tikar akibat hal ini.
Namun setelah kuuraikan kondisi riil potensi, tantangan dan ancaman bisnis media sekarang ini, ternyata si mantan anak buahku yang kini menjadi bosku ini tetap bersikeras untuk mendirikan media online itu. Aku ditawari sebuah mobil untuk operasional, namun kutolak. Aku lebih suka menggunakan kereta api untuk pulang pergi ke rumah.
“Setiap perjalanan selalu punya akhir. Pulang. Rumah,” begitulah suatu kali kutulis di status Whats Appku. Di usiaku yang sudah menginjak kepala lima, aku menyadari bahwa fisik tak bisa diingkari keterbatasannya.
***
Mengingat perjalananku di dunia jurnalistik hingga sekarang ini, tentulah tak bisa lepas
dari berbagai hal. Proses belajar menulis kudapatkan dari banyak orang, banyak buku
dan banyak pengalaman. Dari dunia jurnalistik mengenal dari merah hijau hitam kehidupan, mulai dari hikmah kehidupan hingga kegilaan dunia.
Kusaksikan betapa ada orang yang menghabiskan berpuluh bahkan beratus juta dalam waktu semalam. Ya, jumlah uang yang tak mungkin bisa dikumpulkan oleh sebagian
besar orang di desaku. Seberapapun kerja keras orang desa, tak mungkin langsung mendapatkan uang sebegitu banyak. Bahkan semasa hidup, mereka bisa dibilang tak
mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Apalagi menghamburkan dalam waktu beberapa malam saja. Ah betapa kesenjangan hidup begitu menganga. Beruntung orang-orang di desaku tak mengetahui hal itu.
Dari perjalanan dunia kepenulisanku akhirnya kudapatkan banyak hal yang sebelumnya
hanya kukira hitam putih saja. Betapa hidup bisa seruwet akar pohon kelapa, saling
berserabut, bersengkarut dan tak jelas di mana ujung dan pangkalnya. Tapi hal itu tak terlihat di mata orang umum.
Aku masih ingat ketika seorang anak kiai yang kupanggil Gus itu mengunjungiku di pantura. Ya, ketika itu aku sedang gila-gilanya. Namun yang dilihatnya aku begitu wajar. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ah betapa berbedanya aku dengan dia. Aku di dunia hitam, ia di dunia putih dan mengulurkan tangannya. Dari dialah aku semakin termotivasi untuk terus menulis di waktu muda. Ya, ialah yang memintaku menulis di buletin kecil yang kini mengingatkanku pada proses kreatif dan masa sulit dalam hidupku kulalui. Menjalani dan menginsyafi betapa kemiskinan harus dijalani sebelum masa seberuntung sekarang ini.
“Gus, tapi aku tak bisa nulis yang berbau agama-agama begitu,” kataku kepadanya
waktu itu. Tapi ia terus saja memintaku menulis.
Maka di masa tahun 1990-an ketika mesin ketik menjadi barang mewah, aku mulai menulis.
Karena tak punya barang mewah itu, aku kerap meminjam ke seorang guru atau orang lain yang punya kedudukan, sebelum kemudian sang Gus punya mesin ketik sendiri. Aku menulis dengan gayaku dan konten sesuai pengetahuan, pengalaman hingga imajinasiku.
“Kalau boleh mengaku, saya ini bukan mahasiswa yang ikut kuliah di dua kampus di
Purwokerto. Sering saya seperti itu. Kalau ingin baca buku saya akan pinjam kartu perpus ke teman saya dan saya akan berlama-lama mendekam di perpustakaan sampai teman saya rampung kuliah, dan saya nebeng naik motor pulang lagi,” kataku menjawab betapa penting membaca sebelum kita mau menulis.
Boleh dibilang dari proses kreatif menulis di buletin fotokopian itulah minatku turut terdukung. Apalagi buletin kecil itu pula menjadi wasilah pertemuan jodoh dan jaringan
sosial masa depan teman-temanku. Sayang, hanya beberapa arsip tulisan saja yang
berhasil diselamatkan dan terselamatkan.
***
“Al Mudawamah itu berisi tentang kajian fiqh, masalah agama dan tulisan bebas yang
jadi buku yang kita bedah sekarang ini. Dulu literasi anak-anak muda memang rendah
sekali makanya kami berinisiatif buletin itu dan kami edarkan ke masyarakat khususnya kaum muda. Untuk buku biasanya kami harus pinjam ke teman-teman mahasiswa yang sangat jarang ditemui di desa,” kata temanku yang kini menjadi kiai panggung terkenal sewaktu membedah riwayat-riwayat tulisanku di sebuah forum di tempat temanku yang mantan anggota wakil rakyat tiga periode itu.
Aku masih ingat dengan keterbatasan alat hingga uang, buletin Al Mudawamah itu
selalu rutin diterbitkan. Ada atau tidak ada uang, seperti tidak ada masalah. Temanku
yang kini jadi lurahlah yang menjadi kurir pengantar buletin yang istimewa di
komunitas ormas agama tradisional ini.
“Beliau Gus Chayat berpesan kalau buletin ini harus terus terbit, meskipun rugi,” begitu
kata Rudi, panggilan akrab temanku yang kini jarang disebut dengan nama itu.
Meskipun buletin kecil di sudut pinggiran kota ini diterbitkan dan menjadi ajang kreativitasku, namun ada hal yang terlupa. Ya soal nama Al Mudawamah itu ternyata baru kuketahui sang pemberi nama itu.
“Dulu saat kami sowan ke sejumlah kiai bersama Gus Chayat, Pak Muthohar menyebutkan nama Lestari. Kemudian Al Maghfurlah Habib Idrus menegaskan kepada
kami nama Al Mudawamah, yang artinya persis sama yaitu lestari, istiqomah, terus menerus. Jadi selain menjadi nama pengajian rutin, nama itulah yang menjadi nama buletin yang tulisannya ada di buku ini,” kata Rudi menegaskan.
Ya, siapa sangka ternyata pemberi nama buletin yang menjadi pengiring dan penentu bagian dari perjalanan hidupku adalah ayah dari Ipe Iis yang sering kuajak bergurau secara rasis. Tapi kenapa pas bedah buku di pondoknya Ipe Iis itu tak sekalian riwayat itu terungkap. Mengingat itu, aku hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum sendiri. Selain Maha Serius, ternyata Tuhan juga Maha Lucu. Aku semakin menyadari itu.(Susanto-)*