“Kang, rika duwe pengalaman sing berkesan apa ora karo Habib Idrus?” tanya seorang
lelaki berkacamata minus kepadaku sore ini. Pertanyaan pendek itu tidak serta aku jawab.
Kebetulan juga aku juga baru saja membuka kedai kopi di pinggir kota yang kurintis
bersama kawan sejak tiga tahun lalu.
Kubiarkan si empunya pertanyaan duduk santai terlebih dulu di risban kedaiku. Kuberi
isyarat kepada kawan peracik kopi untuk menawarinya minuman. Servis untuk pelanggan
bagiku adalah nomor satu. Jangan sampai mereka terlalu lama duduk, sementara belum
ada minuman atau makanan di hadapan mereka. Karena yang rugi nanti tidak hanya
pelanggan, tetapi juga aku.
“Ada berapa orang yang nanti ke sini Pak. Apa perlu meja kursi ini ditata sedemikian rupa?” tanyaku seperti abai pada pertanyaan awalnya. Tetapi pertanyaan balikku justru menjadi penting untuk kepentinganku yang sedang berjihad mencari nafkah untuk istri dan anak lelaki ksatriaku.
Setahun pandemi korona mendera, memang banyak yang terdampak, termasuk aku dan
kawan-kawanku. Bagaimana korona membuat omset dan kunjungan ke kedai menurun.
Kawan pemilik kedai di pinggir kota kecamatan wilayah kabupaten bagian barat, bahkan
menyebut prosentasi 60 untuk penurunan omset kedai kopi.
Melambungnya angka kematian yang disebut akibat wabah ini memang kurasakan buka
semata soal angka statistik. Ini benar-benar nyata. Terlebih lagi ketika pemerintah
menerapkan sejumlah kebijakan terkait penekanan angka positif dan mortalitas akibat
wabah.
“Ketika diterapkan pengetatan kegiatan masyarakat, terpaksa aku buka kedai lebih pagi.
Jam 8 pagi aku sudah buka dan aku tutup jam 8 malam. Aku sebelumnya telah didatangi
aparat dua kali, membawa laras panjang juga yang memperingatkan agar aku taat kepada
pemerintah,” kata teman pemilik kedai bercerita pengalamannya.
“Tetapi ini soal perut. Aku baru menyadari betapa kepentingan perut itu sangat sensitif.
Makanya aku coba buka lebih awal. Tetapi memang penikmat kopi malam, adalah penikmat kopi malam. Penikmat kopi malam bukanlah penikmat kopi pagi. Terlepas dari teori ekonomi marketting, aku kira soal selera dan habit penikmat kopi, tak bisa dipaksakan,” jelas teman pemilik kedai lainnya.
Baca Juga : Lepasnya Burung Kesayangan Pak Lurah
Mendengar cerita pengalaman dan keluhan dampak pandemi itu, aku cuma tertawa. Ya,
tepatnya sebenarnya menertawakan nasib yang menimpa kami semua sebagai pemilik
usaha mikro di pinggiran. Bukankah menertawakan diri sendiri adalah cara menghibur
yang paling toleran, daripada menertawakan orang lain?.
Ah. Dengan pengalaman ini semua aku menjadi ingat apa pesan dan pengalaman yang
kualami saat beberapa kali bertemu dan berhubungan dengan sosok kiai sekaligus habaib
yang dihormati ini. Betapa pernyataan sang habib yang akrab dipanggil Abah Idrus itu
masih membekas di benakku, terutama ketika menghadapi persoalan kehidupan yang silih
berganti.
“Tauhid itu nomor satu!” kata Sang Habib beberapa kali datang ke ‘ndalemnya’
***
Sekawanan burung sriti itu berputar-putar mengitari kubah masjid pesantren di
perbatasan kabupaten itu. Padahal sebelumnya tak pernah terjadi peristiwa seperti itu.
Namun hanya sebagian santri saja yang tertarik memperhatikan fenomena yang langka itu.
Apalagi mereka tengah sibuk mempersiapkan acara pengajian rutin Muharam di pesantren
itu.
Pengajian di Bulan Muharam adalah momen pengajian akbar yang rutin menyedot ribuan
jamaah Sang Habib dari berbagai kota. Sebagaimana abahnya Habib Ja’far, Habib Idrus
juga memang terkenal rajin bersilaturahim dengan berbagai kalangan. Sebaliknya, banyak
dari kalangan rakyat, hingga pejabat yang berduyun-duyun sowan menghadap sang habib.
Tak heran, ketika pengajian akan berlangsung maka kesibukan akan terasa di lingkungan
pesantren. Para personel polisi, linmas, santri hingga banser akan terlihat sibuk mengatur
lalu lintas jalan nasional Purwokerto Jakarta. Sebelum hari pengajian tiba, panitiapun telah
dibentuk karena mobil-mobil jamaah pengajian termasuk jamaah thoriqot akan antri di
jalan-jalan desa setempat.
Namun di saat kesibukan menghadapi pengajian itu, sejumlah santri yang dipercaya sang
habib menyiapkan ‘tetek bengek’ acara tengah bingung. Apalagi hari itu entah kenapa
aliran air khususnya sumur pesantren tak begitu lancar untuk mengisi bak-bak untuk
tempat wudlu. Sementara ternyata telah cukup lama wilayah desa yang dikenal desa curah
hujan tinggi itu tak turun hujan.
“Bagaimana ini Kang. Soal air ini perlu segera kita cari solusinya. Apalagi pasti jamaah
membeludak hadir sebagaimana biasanya,” ujar seorang santri ke santri lainnya siang itu. Di awal-awal adanya pesantren tersebut memang para santri sudah terbiasa untuk mengambil air ke sungai untuk keperluan pondok. Namun sekarang sepertinya sudah tak jamannya lagi.
Di tengah santri lain berpikir soal ketercukupan ketersediaan air untuk kepentingan masjid
dan pondok, sejumlah santri lainya terpesona dengan sekawanan burung sriti yang
jumlahnya bisa dibilang mencapai ratusan. Burung yang sekeluarga dengan burung walet
itu mengepak-ngepakan sayapnya yang kecil dengan cepat, tanpa saling bertabrakan.
Entahlah setelah fenomena beratus-ratus burung sriti terbang mengitar kubah masjid dan
pesantren, langit mulai menggelap. Cuaca ekstrem, mungkin sebutannya kalau sekarang
ini. Setelah awan menggantung itulah, kemudian tiba-tiba turun hujan deras sekali. Atas
perintah Sang Abah, para santri diminta untuk mengalirkan talang air ke bak-bak wudlu di
masjid dan pesantren itu.
“Kejadian ratusan sriti yang tiba-tiba datang dan berputar-putar mengelilingi kubah
masjid dan pesantren ini bagi kami adalah sungguh kejadian yang sangat istimewa.
Meskipun hujan tak begitu lama, namun itu sungguh sangat berarti kami yang saat itu
sedang membutuhkan air. Jelang magrib hujan reda dan saat pengajian berlangsung
suasana terang benderang,” ungkap Si Gembul, pengurus pondok yang kebetulan sedari
kecil tinggal di dekat pesantren itu.
***
“Priwe Kang? Ana apa ora?” kata lelaki berkacamata usai meminum teh tawar panas
pesanannya. Pertanyaan itu menyentakku yang ternyata larut dengan berbagai cerita dan
kisah sang habib dan pesantrennnya. Kisah-kisah hikmah yang dianggap di luar nalar sudah jamak diceritakan sang santri ataupun orang-orang lainnya.
“Sebentar,” kataku menjawab singkat.
Kembali aku larut dengan pengalaman saat bertemu dengan sang habib. Tanpa perantara menjadi pemimpin organisasi pelajar tentulah aku tak mungkin bertemu dengan orang-orang istimewa. Saat sowan bersama para senior pembina organisasi, aku mendapatkan banyak wejangan dari sang habib.
Baca Juga : Tentang Abah dan Pertanyaannya
Tapi kalau boleh jujur, wejangan dan pesan beliau yang masih aku ingat adalah tentang pentingnya tauhid. Entahlah apa itu tauhid, latar belakang, latar depan dan begitu pentingnya bagi manusia. Tentulah dengan aku hanya bisa meraba sebatas pengetahuan dan pengalamanku yang mungkin tak sampai sekuku hitam. Apalagi aku memang tak pernah mengenyam pendidikan pesantren yang intens. Aku hanya santri kalong.
Maka terhadap pesannya tentang nomor satunya Tauhid, kukaitkan dengan pengalaman hidupku yang memang berliku-liku. Hitam putih kehidupan bisa dibilang aku jalani dengan siapapun yang terkadang terencana ataupun tidak terencana aku temui. Berbagai akibatpun akhirnya harus aku tanggung, akibat perilakuku itu.
Soal tauhid, akupun mengaca pada diri sendiri yang sekarang justru terdampar sebagai pengelola kedai di pinggir kota, lebih tepat lagi pinggir kali yang sering keruh akibat galian C di hilirnya. Berbeda dengan teman-teman seangkatan, kakak atau adik organisasi yang sebagian sukses malang melintang di jalur politik, akademik hingga ekonomi lainnya.
Ah, entahlah kenapa aku justru beberapa waktu lalu, justru harus bergelut dengan soal politik praktis yang kukira strategis, namun ternyata. Mungkin aku tak cocok, atau mungkin aku, mungkin aku lainnya. Mungkinkah ini juga soal tauhid. Jabariyah, Qodariyah atau Ahli Sunnah Wal Jamaah yang konon menjadi penengahnya. Entahlah.
“Nomor satu itu Tauhid!” itulah perkataan Sang Habib yang seperti menjadi godam besar memukul ke-aku-anku. Akupun masih ingat, aku pernah diberi batu cincin merah oleh sang habib. Tentu orang akan bertanya, apa itu khasiatnya. Dan aku lebih tertarik bukan soal itu. Aku lebih tertarik kenapa banyak orang yang memberi perhatian lebih pada sang habib. Itu terbukti sejumlah orang berpengaruh pada pemerintahan daerah yang pernah aku temui merasa segan dan hormat pada sang habib.
Mungkin soal perkataan Tauhid saja yang bisa kuceritakan pada teman berkacamata itu saja ya. Entahlah menarik atau tidak, yang penting itu pengalamanku dan kesanku kepada sang habib istimewa itu.
Tentulah soal putri-putri sang habib yang manis-manis itu, tak eloklah aku ceritakan. Apalagi sebagai Jawa tulen, tentulah melihat fisik ‘Ngarobi’ tak bisa dipungkiri kami sangat tertarik. Lebih dari itu, tentulah sebagai seorang yang bukan siapa-siapa, tak mungkinlah aku berani untuk melakukan lebih sekadar menaksir, menyimpan kagum atau sekali-kali mencoba mengenalnya.
“Bagaimana Kang. Kok senyum-senyum sendiri?” kata teman berkacamata menyentak lamunanku.
“Yap. Aku punya cerita terkait sang habib. Sebentar,” kataku tegas dan kuputuskan untuk bercerita soal pentinya Tauhid. Soal kenyataan dulu pernah naksir salah satu putri sang habib, tentulah aku hindarkan untuk kuceritakan kepadanya. * (Susanto-3)
Keterangan :
“Kang, rika duwe pengalaman sing berkesan apa ora karo Habib Idrus?” : “Kang, kamu punya pengalaman yang berkesan apa tidak dengan Habib Idrus.
“Priwe Kang? Ana apa ora?” : “Bagaimana Kang? Ada apa tidak?”







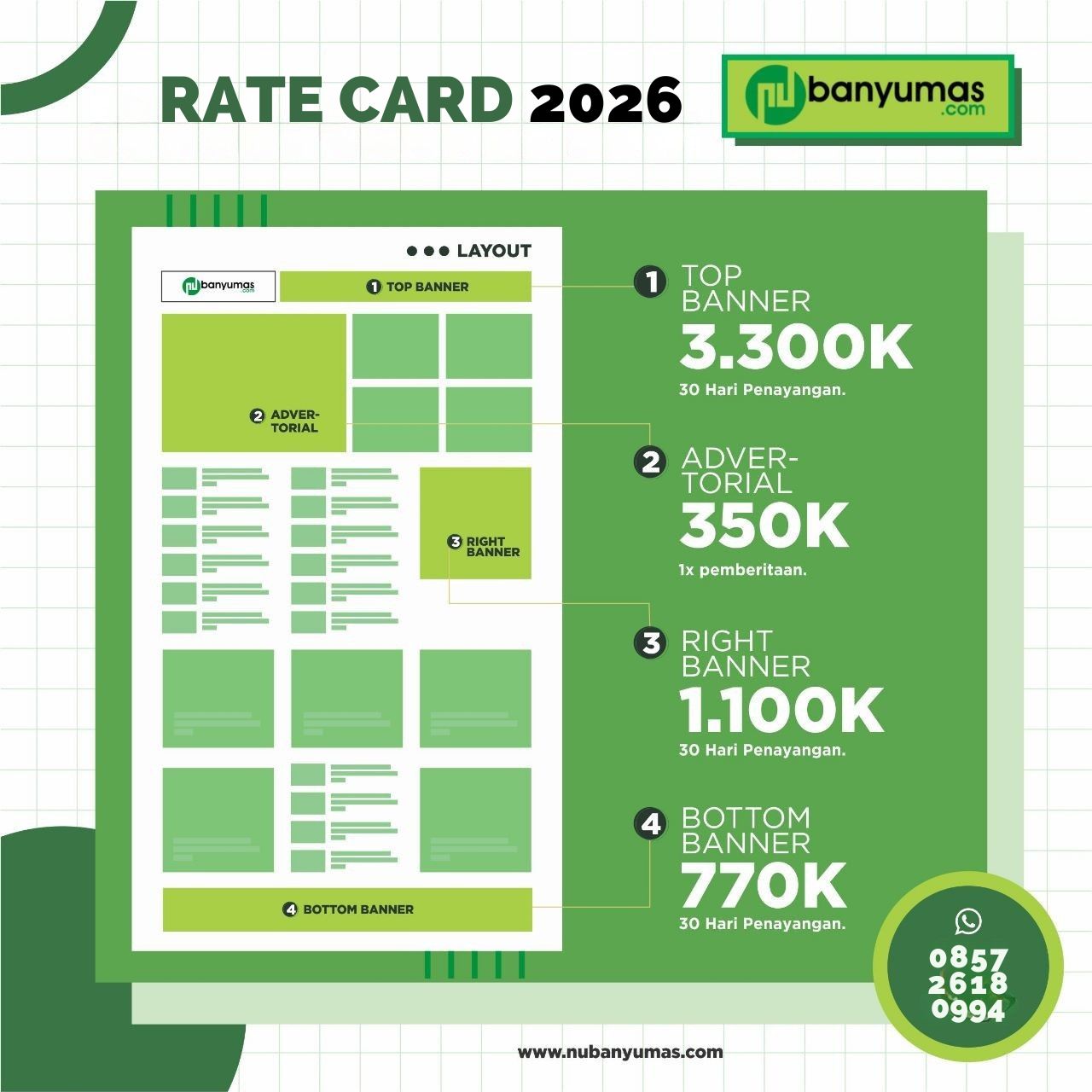







Komentar ditutup