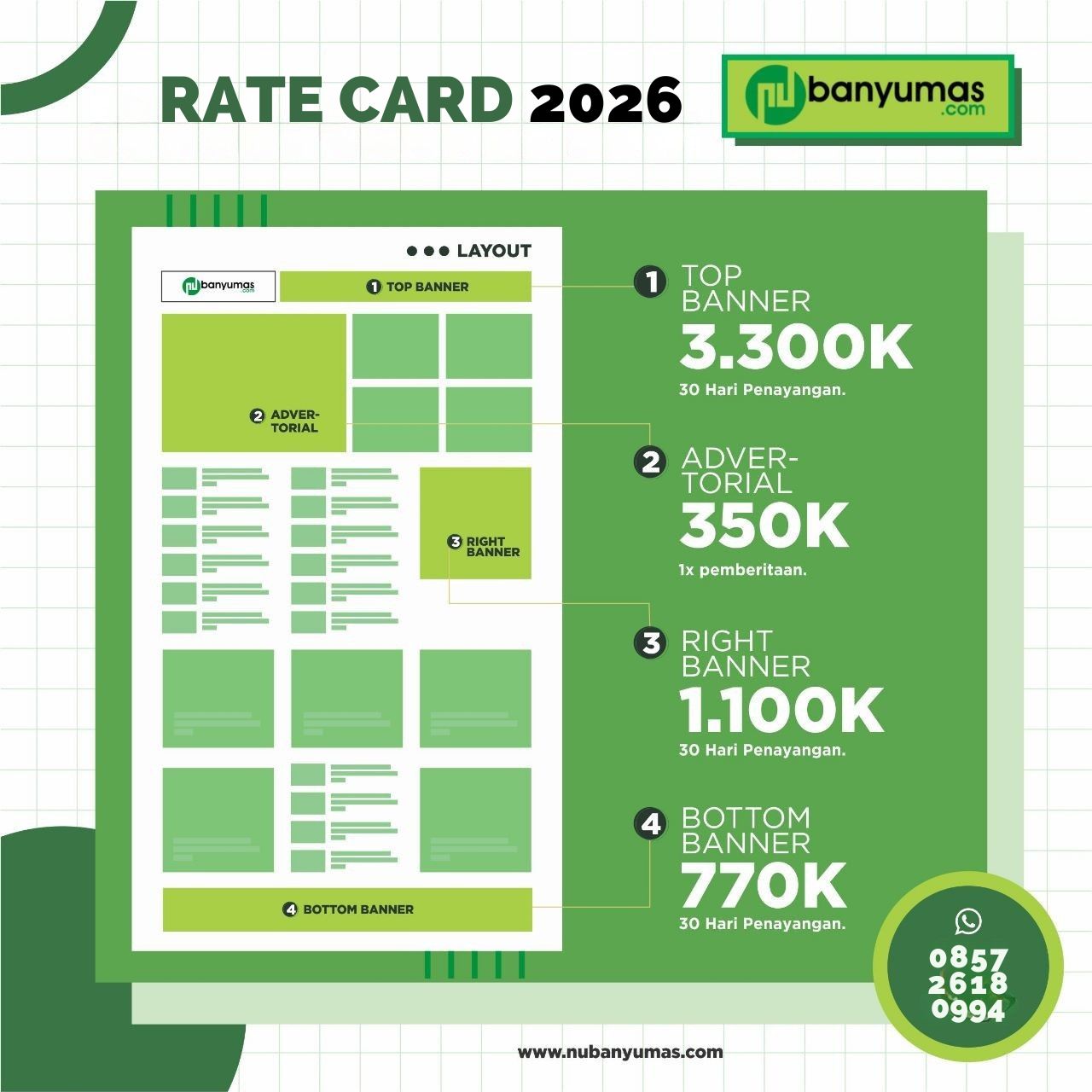PEKUNCEN, nubanyumas.com – Asap panas menyeruak dari wajan besar, membawa aroma kedelai yang baru saja dihancurkan dan dimasak. Udara di dapur sederhana itu terasa lembab, bercampur bau khas tahu yang gurih. Sabtu pagi, 23 Agustus 2025, sekitar pukul sepuluh, langkah saya terhenti di sebuah rumah sederhana di Grumbul Ciroyom, Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Dari balik pintu dapur, kepulan asap tipis menyambut lebih dulu, seolah ingin memberi tahu bahwa di dalam sedang berlangsung sebuah kesibukan.
Dan benar, begitu mata saya menyesuaikan dengan ruangan yang remang oleh uap panas, pemandangan itu menyeruak begitu kuat, Dedi Pratomo, lelaki jangkung berusia 40 tahun, berdiri tegak di samping meja kayu besar, tubuhnya dikelilingi aroma kedelai yang baru direbus. Tangannya cekatan menuangkan adonan tahu panas ke cetakan. Keringat bercucuran di dahinya, tapi wajahnya tetap tenang. Di sisi lain, Siti Maulida, istrinya sibuk mengiris tahu yang sudah jadi, memotongnya dengan presisi agar ukurannya pas.
Dari ruangan sempit nan sederhana itu, ribuan potong tahu lahir setiap harinya, menjadi hidangan banyak orang, menjadi sumber penghidupan untuk keluarga sekaligus juga warisan dari generasi sebelumnya. “Bapak sudah mulai bikin tahu sejak 1985,” cerita Dedi sambil tetap sibuk menuang adonan. “Saya baru nerusin tahun 2014, bapak sudah sepuh. Rasanya sayang kalau usaha ini ditinggal begitu saja.”
Namun, kisah Dedi tentang dapur tahu ini bukanlah cerita sinetron yang ending-nya gampang ditebak. Dedi lahir dari keluarga sederhana dan menikmati masa-masa kecil hingga remaja di Cikembulan. Sejak 1985, sang ayah sudah lebih dulu berkecimpung dalam usaha tahu. Dedi baru resmi mengambil alih usaha itu pada 2014, setelah sang ayah semakin sepuh, tak lagi kuat mengelolanya.
Sebelum kembali ke rumah dan mengikat diri dengan adonan tahu, Dedi sempat menempuh jalan lain, yakni menjadi santri, mondok di pesantren. Tahun 2003, selepas SMP, ia memberanikan diri berangkat sendiri dari Ciroyom menuju Pondok Pesantren Al Falah, Tinggarjaya. “Awalnya saya cuma ngaji di rumah. Tapi melihat teman-teman sarungan itu kok keliahan mulia banget, akhirnya saya ikut mondok juga,” kenangnya.
Tiga tahun lamanya ia hidup dalam irama kitab kuning.Dari pesantren itu ia pulang membawa sesuatu yang tak bisa ditakar dengan angka, kesederhanaan yang menuntun hatinya, kesabaran yang meneguhkan langkahnya, dan semangat untuk mencari nafkah yang halal. Nilai-nilai itu melekat, bukan hanya di kepala, tapi juga di tangan yang kini sehari-hari bergelut dengan adonan tahu.
Hingga kini, kitab kuning seakan masih terbuka di hatinya. Di tengah riuh tungku, uap panas, dan pisau yang membelah tahu, ia tetap menyisihkan waktu untuk mengaji. Setiap Rabu Kliwon, dapurnya ia biarkan istirahat. “Bukan karena malas, mas,” katanya. “Tapi hari itu saya pakai untuk ngaji rutin bersama guru. Itu sudah jadi pegangan.”

Dari Kitab Kuning ke Tahu Kuning
Namun jalan hidup tak selalu lurus. Sebelum benar-benar kembali dan mengikat diri pada warisan keluarga, Dedi sempat mencoba peruntungan lain. Ia membuka usaha jualan es buah. “Waktu itu saya pikir, orang pasti suka yang seger-seger. Jadi saya coba jualan es buah,” ujarnya. Sayangnya, usaha itu tak berjalan mulus. Dagangan sering tak habis, keuntungan tak seberapa, bahkan kerugian kerap menghantui. “Kurang laku, mas. Akhirnya berhenti,” katanya, diselingi senyum tipis. Dari kegagalan itulah Dedi belajar, mungkin Tuhan belum membukaan jalan untuk nya.
Kembali ke Cikembulan, Dedi mendapati dapur tahu bukan sekadar warisan keluarga, melainkan jalan hidup. Sejak resmi mengambil alih warisan sang ayah, ia mulai serius menekuni usaha ini. “Jam satu dini hari kedelai sudah saya rendam,” ucapnya. “Begitu orang lain masih tidur, saya sudah mulai angkat-angkat panci. Capek jelas capek, tapi ini sudah jalan hidup.”
Sekitar pukul 04.30, tahu mulai disiapkan untuk dibawa keluar, kemudian sekitar pukul 08.30 ia sudah pulang. Meski hasil dari julan tahu hasilnya kadang tidak pasti, tapi Dedi menjalaninya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. “Kalau tidak ada tahu, kami bingung mau kerja apa lagi. Ini sudah jalan hidup,” ucapnya.
Dari dapur kecilnya di Cikembulan, Dedi tidak hanya menjual tahu ke pasar dan pelanggan sekitar. Ada satu tujuan yang membuatnya merasa lebih bahagia, yaitu menyuplai tahu ke pondok lamanya, Pondok Pesantren Al Falah. Dalam seminggu, kadang dua kali, kadang tiga kali, ia mengirimkan tahu ke dapur pondok. Setiap kali berangkat, ia selalu menambahkan lebih banyak dari jumlah pesanan. “Namanya juga untuk pondok, mas. Biar santri bisa makan kenyang,” ujarnya sambil terkekeh.
Kebiasaan kecil itu baginya bukan sekadar berdagang, melainkan bentuk bakti. Seakan-akan kitab kuning yang dulu ia baca di pesantren kini menemukan pasangannya dalam tahu kuning yang ia kirimkan kembali ke sana.
Ketika saya menatap tangannya yang penuh bekas goresan kecil akibat kerja keras, saya bisa merasakan beratnya pekerjaan itu. Panas tungku, uap yang menyengat, dan tubuh yang harus terus bergerak tanpa henti. “Tapi alhamdulillah,” katanya lirih sambil tersenyum, “dari tahu inilah anak-anak bisa sekolah. Cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari.”
Istrinya yang dari tadi membantu mengiris tahu menimpali dengan senyum. “Kalau suami sibuk di dapur, ya saya bantu motong-motong. Sudah biasa. Kalau kerja bareng gini rasanya lebih ringan,” ucapnya pelan. Mereka tampak sudah terbiasa bekerja bersama, saling mengisi, tanpa banyak kata-kata. Dari dapur itulah, keluarga kecil mereka berdiri tegak.
Ada ironi sekaligus keindahan dalam hidup Dedi. Ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam menekuni kitab kuning di pesantren, dan kini setiap harinya bergelut dengan tahu kuning di dapur. Namun keduanya sama-sama membentuk hidupnya. Kitab kuning memberinya bekal rohani, sedangkan tahu kuning memberinya bekal untuk menafkahi keluarga.
“Yang penting halal. Itu cukup bagi saya,” ucapnya tegas. Kalimat sederhana itu terasa lebih dalam daripada sekadar semboyan. Ada ketulusan, kepasrahan, dan kebanggaan seorang santri yang kini menemukan jalannya di dunia perniagaan.
Dedi percaya bahwa berdagang adalah pekerjaan yang sangat mulia, bahkan pernah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya, meski kadang terasa berat, ia tetap bahagia. “Setiap potong tahu itu doa, mas,” katanya pelan. “Doa supaya hidup saya barokah, anak-anak sehat, dan orang yang makan juga kenyang.”
Dan pada siang itu, ketika saya pamit untuk pulang, aroma tahu yang masih hangat seakan menempel di baju. Saya menyadari satu hal, bahwa kisah hidup Dedi Pratomo bukan sekadar kisah seorang penjual tahu. Ini adalah kisah tentang warisan keluarga, nilai pesantren, dan keteguhan seorang santri yang menjadikan dapur kecilnya sebagai jalan menuju keberkahan.
Kifayatul Ahyar