A`tina Fatha
“Dika, bangun, Nak, katanya hari ini ada acara temanmu,” sayup-sayup kudengar suara Ibu mengetuk pintu kamar untuk membangunkanku. Kubuka selimut yang semalaman menutup tubuhku. Malam ini terasa begitu dingin. Apalagi rumah orangtuaku ada di kaki gunung Slamet, tepatnya di daerah Kebumen Baturraden Purwokerto. Kuraih jam weker di meja samping ranjangku. Pukul 04.30 sudah waktunya subuh. Sepertinya Ibu dan Ayah akan berangkat jamaah subuh di mushola. Ibu pasti takut aku bangun kesiangan kalau tidak dibangunkan dulu.
“Iya, Bu. Ini sudah bangun,” jawabku tak ingin Ibu khawatir.
“Ibu dan Ayah ke Mushola dulu, ya,” suara Ibu terdengar menjauh.
Segera aku rapikan tempat tidur. Walaupun aku anak laki-laki, sejak kecil telah terbiasa merapikan tempat tidur sendiri. Ibu termasuk yang sangat disiplin mengajarkan anak akan pentingnya kemandirian.
Hari ini, Rabu 23 Desember 2020, aku, Radika Saputra, akan datang ke pengadilan agama untuk menyaksikan sendiri kejadian yang berlangsung terkait teman karibku saat kuliah. Teman saat aku masih merasa sanggup menimba ilmu di fakultas Syariah sebuah perguruan tinggi negeri di kota kami.
Terbayang kenangan ketika masih satu jurusan. Karena hanya berlangsung satu tahun dan setelahnya aku memilih pindah jurusan masih di kampus yang sama. Aku merasa lebih cocok kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Arab daripada harus mempelajari sulitnya jurusan Syariah.
“Kita telat, gaes. Buruan!” seru Aira sambil matanya membulat melihat angka di jam tangannya, kontan membuatku dan Zein yang sedang asik menikmati jus alpukat terkaget. Zein hampir tersedak dibuatnya.
“Jam berapa sekarang?” tanya Zein seolah tak percaya dengan ucapan Air, nama panggilan Aira.
“Jam 10 kosong-kosong,” jawab Air sembari memanyunkan bibirnya.
“Ayolah cabut. Kita udah pernah telat mata kuliah Bu Nova, jangan telat lagi,” ucapku seraya mengambil tas ranselku yang tergeletak di lantai taman kampus. Lalu kami segera menuju ke kelas Bu Nova.
Di banyak kesempatan atau jam kosong, aku, Air dan Zein selalu menghabiskan waktu bersama kala itu. Air, seorang gadis dari keluarga pesantren yang cantik dan memiliki tinggi semampai adalah gadis yang supel dan sangat kekinian. Meski seorang putri kyai, dia terbuka berteman dengan siapa saja. Termasuk dengan aku dan Zein, meski kami dari kaum adam.
Setelah sholat subuh, aku segera mengambil handuk untuk segera mandi. Membantu Ibu menyapu dan mencuci piring sudah menjadi kebiasaanku sejak aku kecil. Terhenti sejenak saat aku masuk Aliyah dan kuliah di Purwokerto. Ibu menghendaki aku indekos saja agar lebih fokus belajar. Kini setelah lulus kuliah dan menjadi guru Bahasa Arab di MTs dekat rumah, aku kembali melakukan aktivitasku membantu Ibu.
Kulihat jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 08.00. Artinya aku harus segera siap-siap karena persidangan akan dimulai jam 09.00. Sebenarnya tak ada yang mengundangku menghadiri sidang ini. Aku hanya ingin saja. Ingin mengetahui kabar Air secara langsung meski mungkin tak perlu dia tahu aku datang. Aku segera meluncur dengan Vario hitamku.
***
“Bagus Wijayanto atau kuasa hukumnya melawan Aira Khanza atau kuasa hukumnya masuk ke ruang sidang 2.”
Suara panggilan itu mengagetkanku dan membuyarkan lamunan tentang Air. Kulihat seorang wanita muda berjilbab bangun dari duduknya.
Ya Alloh, hatiku bagai teriris pisau tajam melihat Air berjalan menuju ruang sidang dengan menggendong bayinya yang baru berusia 23 hari. Kemana perasaan laki-laki itu. Bagus Wijayanto, laki-laki pujaan masa kecil Air yang akhirnya berhasil ia gandeng menjadi suami. Yang Air harapkan menjadi pendamping hidup sampai di surga nanti. Laki-laki yang tiba-tiba datang lagi dalam kehidupan Air dan membuat mimpiku membawa Air ke pelaminan buyar seketika. Astaghfirulloh, dadaku terasa sesak melihat pemandangan yang sungguh tak pernah aku duga sebelumnya.
Wanita muda berkulit putih yang sebelumnya selalu kusebut dalam doa, dan ternyata Alloh menakdirkannya untuk laki-laki lain, sekarang ia dalam kubangan derita. Aku yang kini hanya teman saja mampu dibuat luluh lantah hatiku melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin hati laki-laki itu, suami tercinta Air tega membuat sumur duka di hati Air. Aku tak habis pikir apa yang ada dalam pikiran Bagus Wijayanto saat menggugat Air. Justru di saat Air tengah mengandung buah hati mereka.
Dulu sempat aku lega saat Air mengatakan suaminya sangat sayang dan selalu menuruti keinginannya. Bagus Wijayanto ternyata memiliki karakter yang tidak sebagus namanya. Tidak mampu mempertahankan kesetiaannya hanya karena kata-kata yang dianggap kurang pantas diucapkan Air pada suaminya. Seorang pengayom masyarakat yang sama sekali tidak bisa mengayomi istrinya sendiri. Menggugat seorang istri saat sedang hamil muda, apakah itu adalah laki-laki sejati? Usia kandungan 6 bulan mestinya sedang butuh-butuhnya perhatian dari suami. Tapi Air malah bagai menerima hujan sengatan petir dalam hidupnya. Hingga menyebabkan luka yang begitu dalam.
Semua itu Air tumpahkan dalam pesan whatsapp ketika dirinya terkaget menerima surat gugatan yang datang ke rumah orangtuanya di Ujung Banyumas perbatasan dengan Brebes, saat ia di sana. Bagus yang meminta Air untuk sementara pulang ke rumah orangtuanya dulu, dengan alasan karena dia sering pulang malam untuk kepentingan satgas Covid-19 yang sedang melanda dunia.
Air memasuki ruang sidang diikuti oleh kuasa hukumnya, seorang pengacara senior. Sampai beberapa menit tak kulihat Bagus, laki-laki tak bertanggungjawab itu memasuki ruang sidang. Sungguh dadaku makin sesak dibuatnya. Air, gadis yang dulu selalu ceria, kini kulihat matanya begitu sembab.
Pernah dalam suatu pesan Whatsappnya, dia mengatakan bahwa hujan airmata selalu mengiringi hari-harinya. Menyesal kenapa menuruti Bagus untuk pulang ke rumah orantuanya dan jusru dijadikan Bagus sebagai alasan menggugat Air, bahwa terjadi perselisihan dan Air pulang ke rumah orangtua. Sungguh laki-laki tak punya hati.
Aku menaikkan maskerku agar Air tak mengenaliku seandainya melihatku nanti. Aku duduk di bangku paling belakang sehingga mudah memperbaiki dudukku agar tersembunyi di balik punggung orang-orang yang duduk di bangku depanku.
Masih kuingat saat-saat kebersamaan kami ketika masih satu jurusan. Pergi kuliah bersama, mengerjakan tugas bersama. Bahkan diusir dosen agar kuliah dari luar ruangan juga bersama. Gadis yang berasal dari keluarga pesantren tetapi selalu kekinian. Gadis super energik dan memiliki banyak kegiatan. Namun dibalik kelincahannya itu dia adalah gadis yang sopan dan lemah lembut dan sangat peduli pada orang lain. Maka sangat ganjil jika Bagus menggugat Air dengan alasan Air berkata kasar pada suaminya.
Terbayang saat akhirnya aku memilih pindah jurusan dan Air telah menyelesaikan studinya bahkan telah bekerja sebagai staff di kantor urusan agama, lalu aku menekuni kegiatan sebagai Guru Bahasa Arab. Kami masih sering kumpul jika ada waktu senggang.
Dalam sebuah pertemuan saat itu, Air menyatakan bahwa dia bertemu lagi dengan pangeran masa kecilnya dan berencana akan menikah. Padahal pertemuan mereka baru 2 bulan. Zein kaget dan spontan berkomentar,
“Yakin Lu? Baru ketemu 2 bulan loh. Gila aja. Secepat itu mengenal orang. Nikah loh ini, nggak main-main.” Zein terus saja nyerocos.
“Tapi kan dia teman masa kecilku. Cuma waktu kelas 5 dia pindah mengikuti orangtuanya yang polisi pindah tugas ke Jawa Barat. Sekarang udah pensiun kembali lagi ke kampung.” Bagus memang mengikuti jejak orangtuanya menjadi polisi.
“Kalian kan lama nggak ketemu,” bantah Zein lagi.
“Udah kamu nikahan aja, nanti kalau kamu pisah sama suamimu, aku siap menerima kamu.” Kalimat itu muncul begitu saja dari mulutku saat itu.
“Loh, kamu kok doainnya gitu sih. Doakan biar langgeng donk,” rajuk Air kala itu.
Merekapun menikah dengan pesta pernikahan cukup ramai. Kerabat Kyai Muhaimin, abah Air, hampir semua datang. Teman-teman kantor Bagus pun datang ke pesta di kediaman Kyai Muhaimin. Akupun datang meski saat itu dalam masa penyembuhan sakit hati ditinggal menikah Air. Karena memang aku belum pernah secara langsung mengutarakan perasaanku pada Air. Hingga Bagus datang meluluhlantakkan harapanku.
Sejak menikah memang kami tak lagi bertemu. Tetapi saat menerima surat menyakitkan dari Bagus itu, Air menghubungiku lagi untuk mencurahkan segala rasa yang tak diduganya. Dan sejaki itu, aku terus mengikuti perkembangan kasusnya via dunia maya.
“Sampai sekarang aku masih tidak menyangka, Pung. Di usia yang boleh dibilang masih muda, sudah dipilih sama Allah untuk menjalani ujian ini. Rabu ini akan sidang kelima, mendatangkan saksi dari pihak Bagus. Mohon doanya, Pung, semoga tidak ada kesaksian palsu,” tulis Air dalam chatingnya. Ipung memang nama panggilan khusus dari Air untukku. Berasal dari kata Saputra yang dia menganggap terlalu bagus untukku. Jarang sekali memanggilku dengan nama Dika.
Dadaku kembali sesak membaca pesan whatsapp Air. Terbayang wajah putihnya yang mungkin saja kini sering bermuram durja. Wajah yang dulu selalu berbinar dan ceria. Saat-saat menikmati kebersamaan kami bertiga di kampus saat aku masih sanggup mengikuti berbagai mata kuliah di jurusan Syariah UIN di kota kami. Begitu sering aku, Air dan Zein menghabiskan waktu bersama di taman kampus.
“Kenapa kok nama panggilanmu Air? Nggak Aira aja gitu. Air, biar mengalir seperti Air, gitu?” tanya Zein bertubi-tubi saat awal kami dekat di akhir semester satu. Lalu Air menjelaskan dengan wajah cerahnya.
“Oiya donk, biar mengalir seperti air, hehe.. kata Abah, air itu kan sumber kehidupan. Sesuatu yang penting dan bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin Abah ingin aku bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kali,” jawabnya diikuti tawa renyah seolah tak kenal kesedihan.
Air dan pengacaranya keluar dari ruang sidang. Sayup-sayup kudengar perbincangan mereka, bahwa Bagus dan pengacaranya tidak datang. Beberapa menit kemudian, seorang laki-laki dengan perawakan pendek tapi berisi, yang ternyata pengacara Bagus Wijayanto, datang dan menyatakan bahwa saksi dari pihak Bagus belum siap datang.
Aku sedikit lega dan mulai berharap, persidangan berlangsung lambat sehingga Bagus Wijayanto berubah pikiran, lalu mencabut surat gugatan. Bagaimanapun kecewanya aku dulu, aku tetap ingin Air bersatu lagi dengan suaminya. Bersatu demi masa depan Al Fatih putra semata wayang mereka yang tersia-sia sejak dalam kandungan. Tak tega rasanya melihat bulir air mata yang terus mengalir di pipi Air.
***
Hari ini, Rabu tanggal 10 Februari 2020, aku tepat berumur 27 tahun. Jika tidak sedang pandemi, tentu acara hari ini adalah makan-makan dengan teman kantor. Tapi karena pandemi korona, siswa belum diijinkan belajar di sekolah. Aku bekerja dari rumah dengan memberi pembelajaran secara daring. Jadi aku berencana mau bersih-bersih kolam kecil di taman depan rumah saja. Ibu sudah mengingatkan dari seminggu yang lalu tapi belum sempat aku kerjakan. Ikan-ikan itu sudah perlu air segar setelah sebulan tidak aku ganti airnya.
Urusan kolam ikan mungkin bisa aku tunda agak siangan. Pagi ini sebaiknya bersih-bersih rumah dulu. Sejak Mba Naila menikah otomatis aku menjadi anak semata wayang di rumah ini. Bapak dan Ibu yang mulai sepuh sudah tidak kuijinkan lagi untuk merawat rumah. Aku sudah mengambil alih semuanya. Bapak dan Ibu kusarankan menikmati pensiun dengan perbanyak ibadah.
Setelah selesai membereskan rumah, pukul 10.30, aku siap meluncur ke taman depan. Tapi aku urungkan niat karena hp berbunyi. Sebuah panggilan tak terjawab.
“Air,” gumamku.
“Ada apa, Aira?” tanyaku cepat. Entahlah, sejak Air bercerita tentang masalahnya, aku jadi sering khawatir padanya. Aku sendiri belum berhasil menjawab, mengapa. Apa karena dulu dia adalah orang penting yang selalu kusebut dalam doa, atau karena persahabatan memang begitu kental hingga akhirya dia menikah. Yah, Air dan Zein telah mengakhiri masa lajang mereka, namun aku seolah belum ada tekad bulat ke arah sana. Berkali menjalin hubungan tetapi kandas. Dua bulan lalu aku baru saja mengakhiri hubungan dengan seorang gadis karena tidak direstui Ibuku. Sebelum terlanjur jauh, lebih baik aku mengalah. Aku tidak ingin banyak halangan nantinya jika Ibu dan menantu perempuannya tidak saling cocok.
“Pung, sejak hari ini, aku hanya menjalani hidup dengan anakku,” tulisnya.
Sejenak aku terdiam, mengernyitkan kedua alisku hingga hampir menyatu. Lagi-lagi dadaku sesak. Hari ini Air resmi pisah dengan suaminya. Dia janda muda beranak satu. Aku geram pada Bagus Wijayanto, suami Air yang kini jadi mantan. Aku seolah bisa membayangkan pedihnya hati Air. Suami tercintanya, seseorang yang dia impikan sejak kecil, kemudian bertemu lagi saat dewasa, ternyata tidak sebaik bayangannya di masa kecil.
“Bagus yang sekarang ternyata tidak sebaik yang aku kenal di masa kecil, Pung,” begitu tulisnya dalam chating beberapa hari sebelum sidang saksi yang diam-diam aku hadir di pengadilan.
“Zein benar, harusnya aku lebih lama lagi mengenal Bagus,” tulis Air lagi.
Memang waktu itu aku sempat kaget, hanya dalam waktu 2 bulan setelah bertemu lagi dengan Bagus, Air mantap memutuskan menikah dengan Bagus Wijayanto. Ah, sebenarnya aku sangat tidak suka menyebut nama ini. Nama dan sifatnya begitu bertolak belakang.
***
Delapan bulan berlalu sejak whatsapp terakhir Air di hari berkabungnya, di hari ulangtahunku yang seharusnya aku bahagia didoakan banyak orang melalui ucapan selamat mereka. Tapi hari itu juga seolah menjadi hari paling menyedihkan buatku. Sejak itu Air tak pernah lagi menghubungiku. Akupun tak berani menghubunginya. Dan hari ini, tanpa sengaja aku bertemu Air di alun-alun kota. Kami sama-sama mengikuti upacara hari Santri Nasional. Air tidak membawa jagoannya.
Aku mengajaknya menikmati batagor, jajanan favoritnya saat kuliah dulu. Duduk di bawah pohon beringin besar di pinggir tanah lapang itu. Dalam suasana yang cukup santai aku mencoba menelusuri isi hatinya kini. Aku mengutarakan perasaanku dulu sembari bercanda. Aku berharap dia tahu bahwa perasaan itu kini masih ada dan bisa terus tumbuh jika mendapat siraman air dari Air. Lalu dalam situasi yang lebih serius Air menjawab gurauanku.
“Aku lebih suka kita menjadi sahabat saja, Pung. Aku belum terpikir untuk merajut lagi benang-benang itu. Bukan karena aku belum bisa move on. Tapi mungkin lebih bahwa sekarang aku menikmati kenyamanan hidup dengan Al Fatih saja. Entah sampai kapan rasa nyaman seperti ini. Yang jelas, bagiku kamu sahabat terbaik. Dan aku tak ingin ada kesempatan kita untuk saling melukai. Dengan menjadi sahabat, aku berharap kita lebih banyak kesempatan menebar kebaikan dan bukannya saling menyakiti.”
Aku tersenyum kecut sembari meneguk es tehku yang mulai hilang manisnya. Aku tidak bisa memaksakan kehendak. Mendoakan Air dari jauh sebagai sesama muslim mungkin itu lebih baik. Mobil pesantren milik keluarga Air telah terparkir di jalan raya dekat kami duduk. Air pamit pulang, akupun bersiap pulang dan siap untuk menemukan bidadari surgaku.*
A`tina Fatha. Lahir di Banyumas, 24 November 1983.Menempuh pendidikan terakhir di jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Semarang. Founder Rumah baca dan Taman Belajar ‘PELANGI SEJUTA BINTANG (PSB)’. Pengajar mata pelajaran IPA di MTs Miftahul Huda Rawalo. Penulis buku antologi cerpen ‘Padang Patah Hati’, ‘Tiga Kata Ajaib’, ‘Penjilat Ludah Mawar’,’Eidetik’, ‘The Spirit of 2020’, ‘The Stories of Move On’, ‘Jangan Panggil Aku Penulis’, ‘Peluk Hangat Adik dan Kakak’, ‘Antara Cinta, Cita-cita dan Sahabat’, ’Album Merah Jingga’, “Edelweis dan Secangkir Kopi’, ‘Masker dan Layangan Baru Nuril’, ‘Sahabat Lintas Batas’, ‘Anak-Anak Katulistiwa’, ‘Dongeng Fabel Karakter Cerita Minggu Pagi’, dan beberapa antologi dalam proses terbit. Sekarang tinggal di Desa Tipar Rt 04 Rw 10, Rawalo Banyumas, email: atinafatha24@gmail.com.







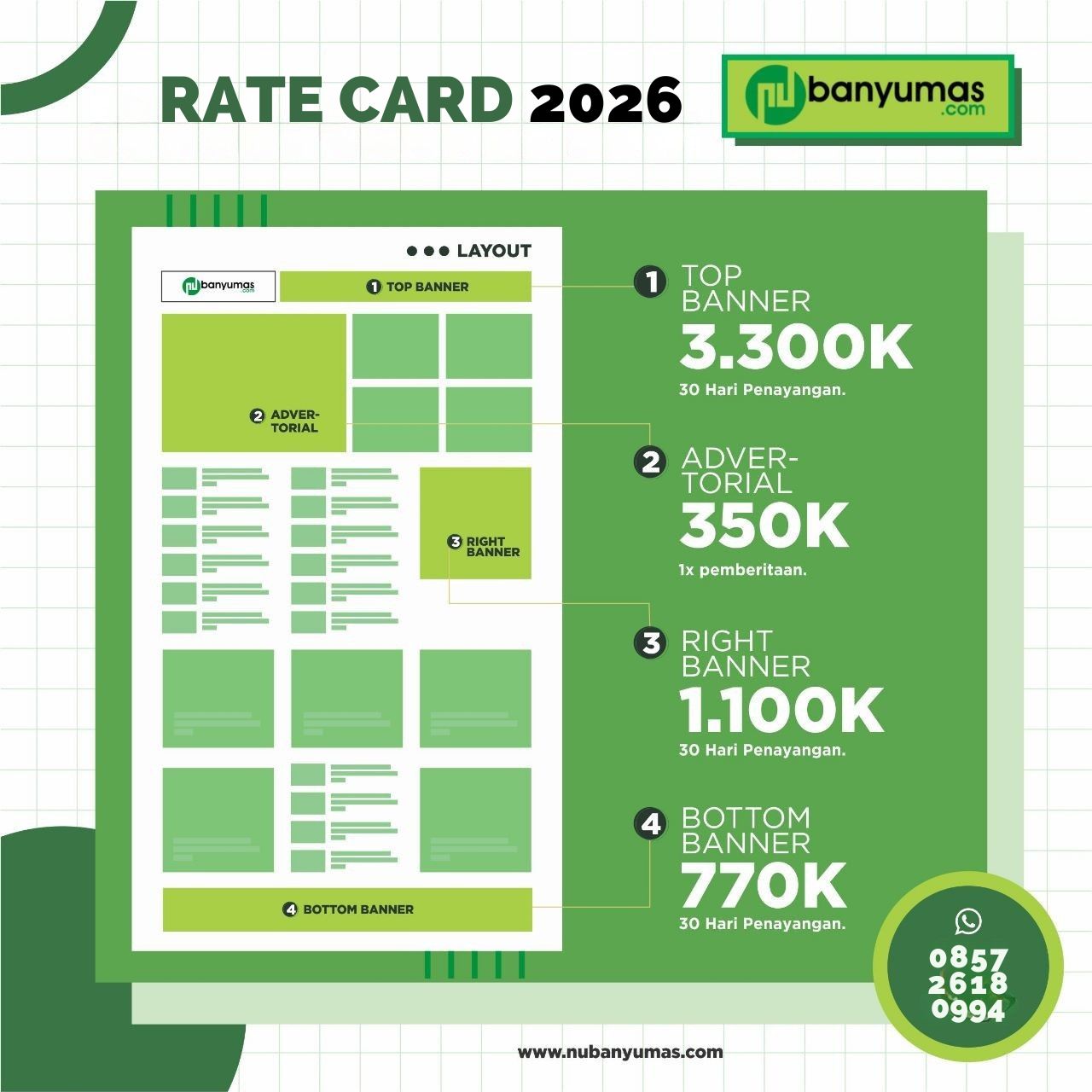







Makasih 🙏
keren
Terima kasih Bu Mien, berkenan mampir.
Terima kasih Bu..
Masyaallah, seru. Panjang pisan, alur yang meliuk-liuk indah.
Kerreen mba, bagus banget
This is good
Good
Bagus banget mba
Makasih supernya… Ayo mba, viralkan nubanyumas.com lewat karyamu..hihihi…
Super sekaliii mbaaa