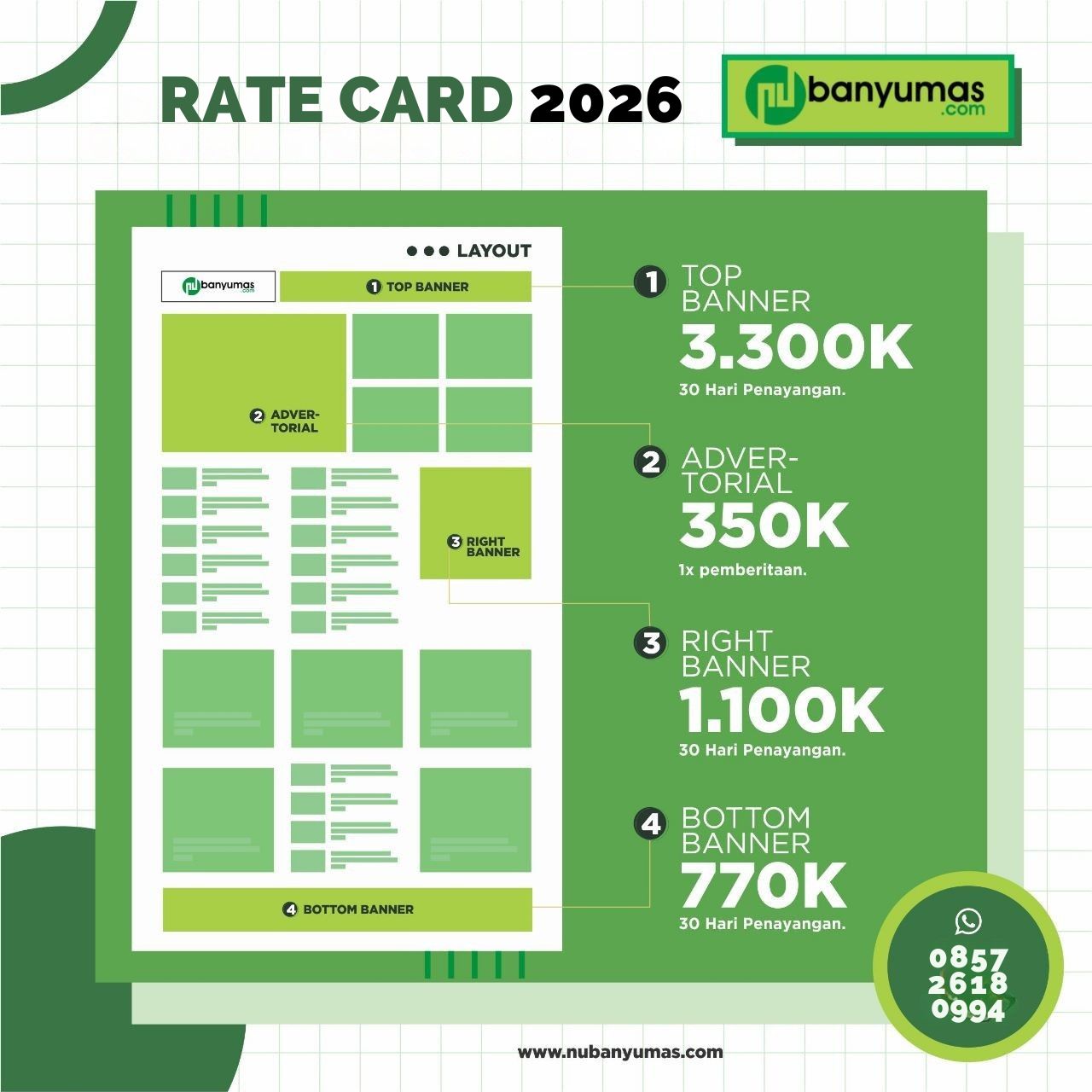Perbedaan corak ilmu pesantren dan perguruan tinggi, adalah bagaimana mereka memperlakukan ilmu.
Di pesantren ilmu dipelajari sebagai sebuah keyakinan.
Bagi kalangan pesantren, ilmu adalah “substansi”, bukan “objek riset” yang dijadikan sasaran penelitian untuk membantah atau membuktikan suatu tesis tertentu dengan metode tertentu.
Kalau kita belajar fiqh misalnya, kita mempelajarinya supaya paham fiqh dan mempraktekkannya sehari-hari.
Ia tidak dipandang sebagai sebuah, katakanlah “metode” yang digunakan secara netral untuk meneliti hal apa pun.
Seperti seorang sosiolog modern memakai ilmu sosiologi sebagai pisau analisis untuk melihat perubahan-perubahan sosial.
Baca juga: Karantina Santri, Suka Duka Penuntut Ilmu
Di pesantren, ilmu disikapi sebagai objek yang “dipeluk” dan diugemi (pegang erat), dan dijadikan penunjuk jalan yang memandu kehidupan.
Berbeda dengan tradisi pesantren, watak ilmu di perguruan tinggi modern cenderung berjarak, memisahkan antara ilmu dengan “komitmen keyakinan” para ilmuwan. Non-faith based, atau “faithless”.
Di perguruan tinggi, ilmu adalah alat netral yang bisa dipelajari siapa saja, dan bisa digunakan sebagai pisau untuk menelaah apa saja. Karenanya ia berjarak.
Bukankah menelaah mengandaikan adanya jarak antara penelaah dan objek yang ditelaah ?
Karena bagi kalangan pesantren, ilmu adalah substansi.
Sehingga ubstansi ilmu yang dipelajari di pesantren berkaitan dengan kitab suci, maka segala ilmu yang berkaitan dengannya dianggap sakral.
Ilmu nahwu (gramatikal) dan sharaf (morfologi) misalnya. Ilmu alat ini sebenarnya tak punya nilai sakralitas pada dirinya sendiri.
Sebab sebagai alat, mestinya ia netral. Tetapi karena ilmu ini adalah ilmu yang dipakai untuk memahami ilmu-ilmu sakral, maka ia menjadi sakral lighairiha (karena faktor lain), bukan sakral lidzatiha (karena dirinya sendiri).
Karena kelimuan di dalam tradisi pesantren dianggap sakral, maka guru-guru yang mengajarkannya pun harus memenuhi kualifikasi moral tertentu.
Akhlak pribadi para guru menjadi penting di mata kalangan pesantren.
Lebih jauh karena “kecipratan” sakralitas, buku-buku berbahasa Arab, bertuliskan huruf Arab menjadi lebih sakral karenanya ia harus diletakkan di atas buku yang lain misalnya.
Bahkan meletakkan pena di atas kitab kuning dianggap bisa mengurangi keberkahan kita dalam menuntut ilmu, karena dianggap tidak menghormati alat ilmu.
Sampean mungkin tertawa, tapi coba tengok kitab-kitab seperti Ta’lim Muta’alim. Di sana memang ada ajaran begitu.
Pandanglah itu secara proporsional, ndak usah sok modern dan kemaki sehingga muncul sikap memandang rendah nilai orang lain.
Walhasil, dalam konteks akademis modern, hubungan ilmu dan ilmuwan cenderung instrumental.
Dalam arti seorang ilmuwan adalah orang yang memperlakukan ilmunya sebagai instrumen atau alat saja baginya.
Mungkin seperti hubungan antara penjual dan pembeli.
Saya beli baju tak peduli apakah secara personal penjualnya saleh apa tidak, salatnya rajin apa tidak, saya tak terlalu mengurus itu.
Sebab urusan itu dalam nalar akademis modern, adalah masalah pribadi, tak ada kait-kelindannya dengan keputusan saya membeli baju dari penjual bersangkutan.
Ini sangat berbeda dengan tradisi pesantren.
Orang dari kalangan pesantren tentu mikir-mikir dulu, bahkan cenderung menolak makan jajan pasar misalnya. Tapi itu dulu, pesantren salaf, kalau sekarang entah.
Oleh: Abdul Mukti, mahasiswa jurusan Hukum Syari’ah UNU Purwokerto