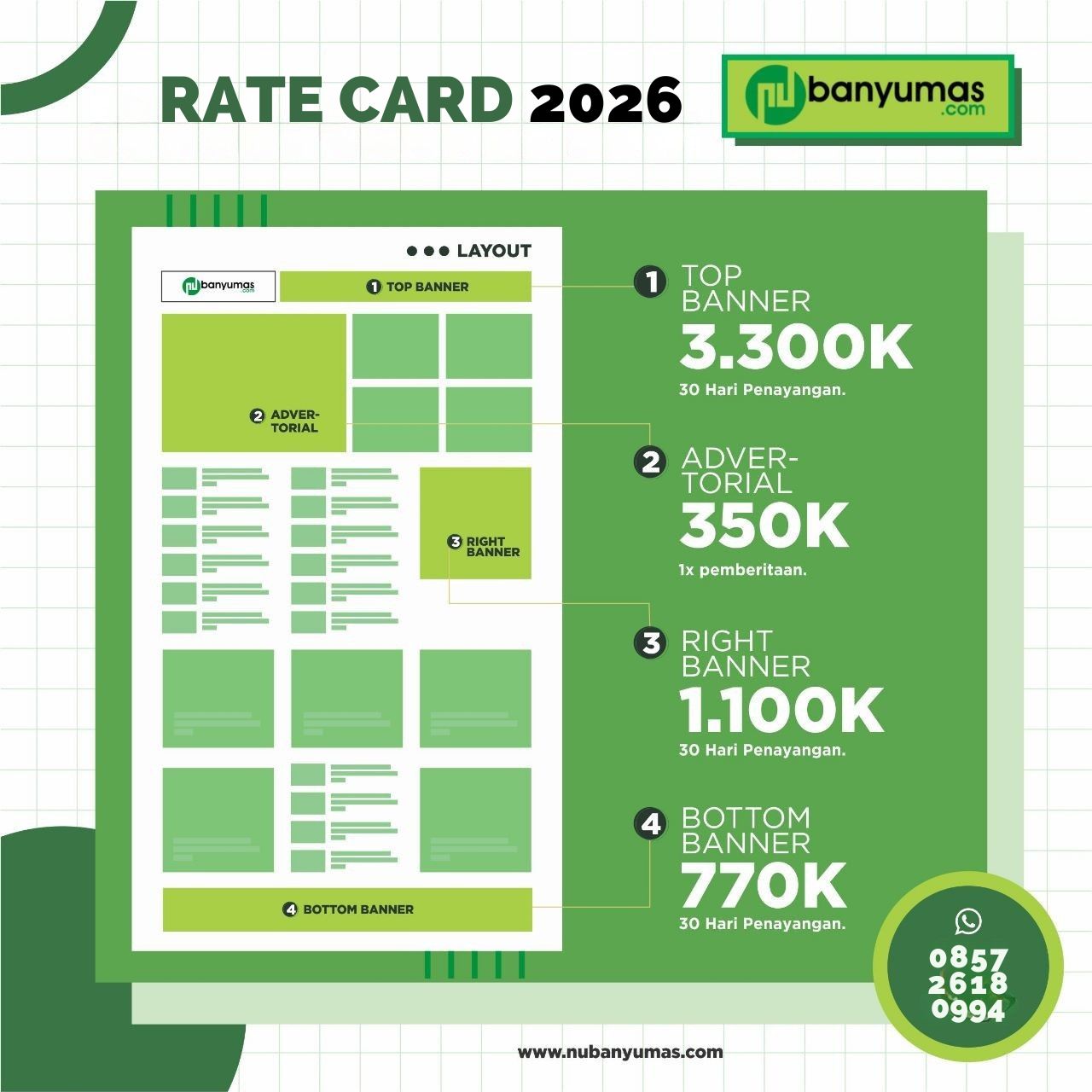SORE selepas magrib seorang anak 4,5 tahun menangis di hadapan mamanya.
“Ma, bapa jadi habib ya?” kata anak perempuan berperawakan mungil itu.
“Apa?” tanya ulang sang ibu pada anak itu. Tetapi anak perempuan itu malah tambah menangis.
“Bapa evolusi jadi habib!”katanya lebih keras lagi.
Mendengar itu sang ibu bertatap pandangan sang bapak anak. Di tengah derai tangis sang anak, suami isteri itu saling tertawa.
Kosakata habib yang sangat ketimuran dan evolusi yang identik dengan kebaratan itu bercampur di lisan anak TK yang berada di desa perbatasan yang kebetulan hidup berdampingan keluarga habaib dan Syarifah itu.
Kebenaran juga anak itu bersekolah bersama dengan anak salah satu habib muda yang dihormati sebagai pengasuh pesantren di desa itu.
“Apa kira-kira yang ada dalam pikiran anak ini ya?” tanya sang suami pada istrinya. Sang istri hanya mengangkat kedua bahu dan mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum.
Di tengah mencari jawaban untuk menenangkan sang anak, sang bapak tersenyum sendiri. Sebagai seorang Jawa tulen tentulah ia tak bisa berubah wajah menjadi Ngarabi.
Kalau evolusi butuh jutaan tahun dan untuk oplas tentulah biayanya sangat mahal. Dan itu adalah pikiran konyol tentunya.
Menghadapi peristiwa itu sang suami langsung flashback ketika sepuluh tahun lalu saat ia menjadi wartawan muda di surat kabar lokal.
Suatu malam itu ia mendapatkan tugas meliput pemberitaan untuk memperkuat kersama klien iklan di suatu desa di dekat Makam Wali yang dulu diziarahi Gus Dur.
Malam itu ia meliput kegiatan sholawat dan pengajian untuk umum yang diadakan majelis taklim yang dihidupkan seorang habaib yang dihormati daerah setempat.
Di tengah mencari lokasi mengambil foto dengan angle yang menarik dan kolosal iapun menyeruak di tengah kerumunan para pengunjung anak-anak.
Sambil menunggu momen ‘mahalul qiyam’, ia berdiri di tengah anak-anak desa setempat. Ada yang memakai peci yang telah mengelupas warnanya, peci bapak yang kebesaran. Ada yang memakai peci putih dan lainnya.
Giliran momen mahaluk qiyam tiba, anak-anak itupun saling berbisik untuk berdiri bersama sbil berdoa. Mata-mata mereka memandang berjajaran wajah wajah dengan hidung mancung dan tinggi besar di panggung utama. Di Nagara itu juga ada habib-habib kecil.
“Besok kalau sudah besar cita-citaku jadi habib,” kata seorang anak di samping sang wartawan. Lainnya mendorong kepala anak itu. Tapi anak itu hanya tersenyum dan sambil memandang tanpa kedip jajaran para habaib dan kiai desa setempat di panggung depan.
Peristiwa itu benar-benar terjadi puluhan tahun silam dan pernah ia ceritakan kepada sahabat dan isterinya tersebut. Dan sore tadi ia mendapatkan hal serupa terjadi pada anaknya yang masih kecil.
Diam-diam sang isteri merenung dan tersenyum dan mengusap serta meniup ubun-ubun sang anak yang digendong dengan sayangnya.
Sang suami hanya tersenyum dan menerka apa kira-kira doa yang dilangitkan kepada Tuhannya yang mencipta segala rupa manusia dari Ngarobi wal Ngajami.
Mungkinkah sang isteri berdoa agar kelak sang anak diperistri habaib? Seperti saudara kakeknya yang diperistri sang Sayid di kampungnya. Ah, terserah lah yang penting adalah doa baik yang dipanjatkan kepada Gusti Allah.
Mungkin para arwah kakek, nenek dan buyutnya yang malam Jumat tadi tilik umat, tersenyum melihat tingkah dan harapan doa sang cucunya itu.
Sang bapak pun tersenyum, dan berpamitan pada sang isteri untuk berangkat rutinitas Yasin Fadilah yang konon turut dirintis oleh kiai setempat dan sayid di masjid jami’ desa setempat.
Lahir rejeki jodo dan ‘pati’ tidak dapat ditawar. Suami isteri di waktu yang paling intim itu kembali saling bertatap pandang dan tersenyum.
Mereka melangitkan doa semoga anak-anaknya bisa menjadi orang baik termasuk seperti para habaib, syarifah, para tokoh masyarakat, kiai dan warga di desa perbatasan yang telah saling ‘berangkulan’ tanpa jarak menghidupkan kehidupan berakhlakul Karimah dengan pendidikan dan dakwah.***